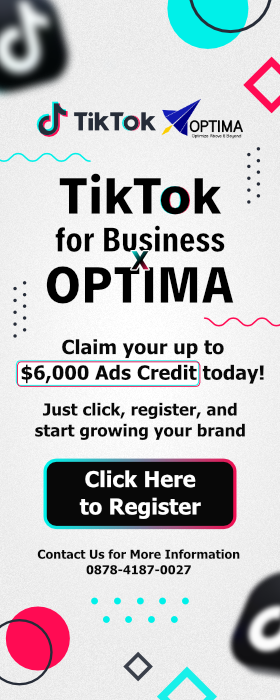CampusNet – Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI kembali menjadi sorotan setelah menjatuhkan sanksi terhadap tiga anggota DPR — Ahmad Sahroni, Nafa Urbach, dan Eko Hendro Purnomo (Eko Patrio). Ketiganya diskors selama 3 hingga 6 bulan tanpa hak keuangan, menyusul laporan dugaan pelanggaran etik yang dianggap mencederai martabat lembaga legislatif.
Sekilas, keputusan ini tampak tegas. Tapi jika dicermati lebih dalam, langkah MKD justru mengungkap problem yang lebih fundamental: parlemen kita tampaknya hanya kuat dalam simbol, tapi lemah dalam substansi.
Antara Hukuman dan Gimmick Moral
Skorsing selama beberapa bulan jelas bukan akhir dunia bagi anggota DPR dengan privilese politik dan finansial besar. Tanpa mekanisme pemulihan moral yang jelas, sanksi semacam ini sering berakhir sebagai ritual politik, bukan proses pembelajaran etika.
Publik mungkin senang mendengar kata “diskors”, tapi apakah skorsing itu benar-benar berdampak? Tidak ada evaluasi publik, tidak ada kewajiban permintaan maaf terbuka, dan tidak ada transparansi tentang pelanggaran yang dilakukan. Yang tersisa hanya headline berita dan rasa puas sesaat, seolah etika sudah ditegakkan.
Padahal, pelanggaran yang dilaporkan bukan sekadar soal perilaku personal. Dalam kasus ini, beberapa anggota DPR disorot karena gaya hidup hedon, pernyataan publik yang tidak sensitif, hingga tindakan yang dianggap mempermalukan lembaga. Artinya, ini bukan kesalahan individu semata — melainkan gejala penyakit sistemik di tubuh parlemen: kerapuhan moral yang diabaikan selama bertahun-tahun.
MKD: Lembaga Etik atau Penjaga Citra?
Dalam teori politik, lembaga etik seperti MKD seharusnya menjadi benteng terakhir moralitas parlemen. Tapi di Indonesia, MKD sering berfungsi seperti penjaga gerbang citra, bukan penjaga integritas.
Selama pelanggaran tidak mengancam reputasi institusional secara publik, kasus cenderung sunyi. Tapi begitu viral di media sosial, MKD tiba-tiba “bergerak cepat”.
Reaktif, bukan preventif.
Seremonial, bukan sistemik.
Inilah paradoks terbesar DPR: etika hanya ditegakkan ketika sorotan publik tak lagi bisa dihindari.
Krisis Kepercayaan dan Kebutuhan Reformasi
Sanksi terhadap Sahroni, Nafa, dan Eko seharusnya menjadi momentum untuk merevisi cara DPR memahami akuntabilitas moral. Bukan dengan menambah pasal hukuman, tapi dengan membangun sistem yang mencegah pelanggaran terjadi sejak awal — lewat transparansi keuangan, kode etik digital, hingga pengawasan independen dari luar parlemen.
Sayangnya, hal-hal seperti ini jarang dibahas di ruang sidang MKD. Fokusnya tetap pada “siapa yang salah”, bukan “mengapa sistem memungkinkan kesalahan itu terjadi.”
Selama etika diperlakukan sebagai formalitas dan bukan kesadaran politik, setiap skorsing hanya akan menjadi teater moral yang diulang setiap periode pemilu.
Kesimpulan: Tegas di Permukaan, Runtuh di Dalam
Putusan MKD DPR terhadap tiga anggota dewan memang penting sebagai langkah simbolik. Tapi tanpa pembenahan sistemik, simbol itu tak lebih dari tameng reputasi di tengah menurunnya kepercayaan publik terhadap lembaga legislatif.
Etika politik seharusnya bukan alat kosmetik untuk menutupi cacat institusional, melainkan cermin bagi kekuasaan untuk terus berkaca — dan memperbaiki diri.
Selama parlemen masih sibuk menjaga wajah, bukan nurani, maka setiap sanksi hanya akan terdengar seperti tepuk tangan palsu di panggung moral yang kosong.