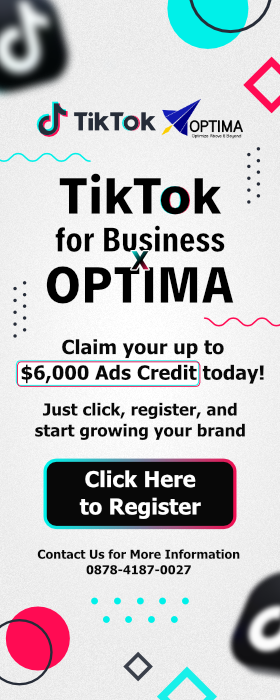CampusNet – Nama Soeharto kembali mengisi headline nasional.
Namun kali ini bukan karena sejarah kelam Orde Baru,
melainkan karena gelar baru: Pahlawan Nasional 2025.
Presiden Prabowo Subianto, yang juga menantu Soeharto, resmi menetapkan sang mantan presiden ke-2 RI sebagai salah satu penerima gelar kehormatan tersebut.
Keputusan ini sontak memicu kontroversi besar — dari masyarakat sipil, aktivis HAM, hingga kalangan mahasiswa.
Banyak pihak menilai keputusan ini sebagai bentuk upaya negara menulis ulang sejarah.
Seolah, semua luka dan pelanggaran masa lalu bisa dihapus hanya dengan satu tanda tangan.
Antara Pahlawan dan Penguasa
Soeharto memang sosok yang kompleks.
Bagi sebagian orang, ia dikenal sebagai Bapak Pembangunan — simbol stabilitas dan kemajuan ekonomi.
Namun bagi banyak lainnya, Soeharto adalah wajah otoritarianisme,
yang identik dengan pembungkaman pers, penculikan aktivis, dan korupsi sistemik.
Kini, ketika pemerintah justru mengangkatnya sebagai pahlawan, muncul pertanyaan mendasar:
Apakah yang dimaksud “pahlawan” di negeri ini adalah mereka yang berkuasa, bukan yang berjuang?
Rakyat yang Tak Pernah Didengar
Yang membuat masyarakat geram bukan hanya karena gelarnya,
tapi karena cara pemerintah mengabaikan suara publik.
Gelombang penolakan datang dari berbagai arah — media sosial, organisasi mahasiswa, dan lembaga HAM — namun keputusan tetap dijalankan tanpa dialog terbuka.
Kita jadi bertanya-tanya:
apakah demokrasi hanya berlaku saat pemilu,
sementara setelahnya rakyat kembali jadi penonton?
Dalam sejarah Indonesia, suara rakyat sering kali kalah oleh kalkulasi politik.
Dan kasus ini menunjukkan bahwa, bahkan setelah reformasi,
pendengaran negara terhadap rakyat masih selektif.
Ketika Sejarah Jadi Alat Politik
Pemberian gelar ini tidak bisa dilepaskan dari konteks kekuasaan hari ini.
Prabowo, yang kini presiden, pernah menjadi bagian dari rezim Soeharto.
Maka langkah ini bisa dibaca sebagai rehabilitasi simbolik,
sebuah cara untuk “membersihkan” warisan politik masa lalu.
Namun yang berbahaya adalah pesannya:
bahwa sejarah bisa dinegosiasikan.
Bahwa pelanggaran HAM, korupsi, dan represi bisa ditutup dengan gelar kehormatan.
Dan kalau itu terus terjadi, maka bukan hanya sejarah yang kehilangan makna — tapi juga keadilan.
Penutup: Siapa yang Menulis Sejarah Indonesia?
Ketika negara bisa menyebut pelaku sebagai pahlawan,
mungkin kita sedang hidup di masa di mana kebenaran tak lagi penting.
Rakyat sudah menolak, tapi siapa yang mendengar?
Karena di negeri ini, yang menentukan siapa “pahlawan” bukan sejarah,
tapi kekuasaan.
Maka tugas kita — generasi muda, akademisi, dan jurnalis — bukan hanya mengingat, tapi melawan lupa.
Karena jika kita diam hari ini,
besok bukan hanya kebenaran yang hilang —tapi hak kita untuk menuliskannya.