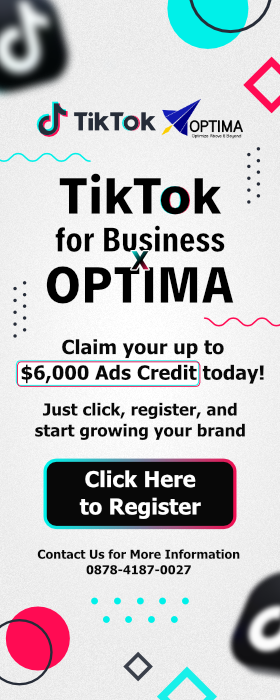CampusNet – Ketika publik masih memperdebatkan pantas atau tidaknya Soeharto mendapat gelar Pahlawan Nasional, ternyata bukan hanya dirinya yang punya rekam jejak kelam di balik penghargaan negara. Nama Sarwo Edhie Wibowo, tokoh militer yang dikenal berperan besar dalam penumpasan Gerakan 30 September 1965 (G30S), juga pernah mendapat penghargaan serupa.
Namun, di balik gelar itu, ada catatan sejarah yang tak bisa dihapus begitu saja — dugaan keterlibatannya dalam pelanggaran HAM berat di masa pasca-1965, ketika ratusan ribu orang dituduh simpatisan PKI dan dibunuh tanpa proses hukum.
Militerisme yang Diganjar Penghormatan
Sarwo Edhie Wibowo dikenal sebagai komandan RPKAD (kini Kopassus) yang memimpin operasi militer setelah peristiwa G30S. Banyak catatan sejarah menyebut, pasukannya memainkan peran kunci dalam pembersihan besar-besaran yang menewaskan ratusan ribu orang di berbagai daerah.
Namun ironisnya, alih-alih dievaluasi atau dikritisi, negara justru memberi penghargaan.
Ketika nama-nama seperti Sarwo Edhie Wibowo diangkat jadi pahlawan, kita dihadapkan pada pertanyaan moral: apakah ukuran kepahlawanan hanya ditentukan oleh keberpihakan pada penguasa, bukan pada nilai kemanusiaan?
Lupa atau Sengaja Melupakan Luka 1965?
Tragedi 1965 adalah salah satu bab tergelap dalam sejarah bangsa. Tapi bukannya direfleksikan, justru seringkali direvisi. Ketika pelaku militer mendapatkan gelar kehormatan, pesan yang tersirat jelas: negara lebih memilih menormalisasi kekerasan daripada mengakui luka sejarah.
Di titik ini, kita perlu bertanya — bagaimana nasib para korban dan keluarganya? Apa artinya “pahlawan nasional” bila di saat yang sama masih ada mereka yang kehilangan anggota keluarga tanpa keadilan?
Kepahlawanan yang Dipolitisasi
Tak bisa dipungkiri, pemberian gelar pahlawan sering beririsan dengan politik kekuasaan. Sarwo Edhie Wibowo adalah mertua dari Presiden ke-6 RI, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Fakta ini menimbulkan pertanyaan publik: apakah penghargaan tersebut murni untuk jasa, atau bagian dari politik rekonsiliasi dan legitimasi sejarah?
Sayangnya, di Indonesia, penghargaan semacam ini sering kali menjadi cara untuk menulis ulang sejarah — menjadikan yang kontroversial tampak heroik, dan yang terluka semakin dilupakan.
Meninjau Ulang Arti “Pahlawan”
Gelar pahlawan seharusnya tak sekadar simbol atau penghargaan politik. Ia seharusnya mencerminkan nilai kemanusiaan, moral, dan keberanian melawan ketidakadilan. Tapi ketika pelaku kekerasan di masa lalu justru dimuliakan, maka istilah “pahlawan” kehilangan maknanya.
Sejarah tak akan pernah benar-benar mati.
Yang kita pilih untuk kenang — atau sengaja kita lupakan — akan menentukan wajah moral bangsa di masa depan.
Baca juga: Soeharto Jadi Pahlawan Nasional: Ketika Kebenaran Kalah oleh Kekuasaan