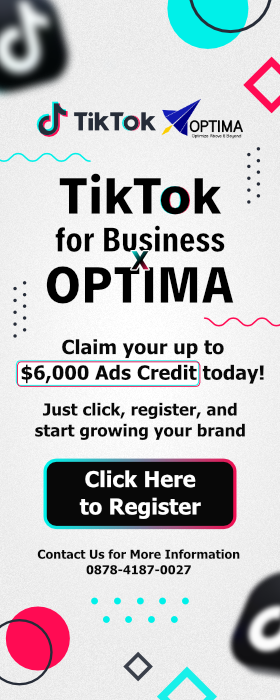CampusNet – Publik kembali diguncang dengan kabar mengejutkan dari SMAN 72 Kelapa Gading, Jakarta. Seorang siswa diduga membuat bom rakitan dan menyimpannya di lingkungan sekolah. Meskipun, tidak ada korban jiwa, namun peristiwa ini menimbulkan pertanyaan besar: apa yang sebenarnya terjadi di baliknya?
Menurut laporan awal kepolisian, motif pelaku diduga karena perundungan atau bullying yang terjadi di lingkungan sekolah. Jika benar, kasus ini menambah panjang daftar persoalan psikologis dan sosial di dunia pendidikan Indonesia.
Fenomena ini bukan sekadar soal keamanan sekolah, tapi juga kegagalan kita dalam menciptakan ruang aman bagi remaja untuk berbicara dan didengar. Banyak siswa merasa sendirian, ditekan, dan tidak punya tempat untuk menyalurkan rasa frustrasinya — hingga akhirnya meledak, dalam arti yang sesungguhnya.
Game Perang Jadi Kambing Hitam Lagi
Pasca kejadian ini, muncul pernyataan dari Presiden Prabowo Subianto yang mempertimbangkan untuk membatasi game bertema perang. Alasannya, permainan semacam itu dinilai dapat menanamkan semangat kekerasan pada generasi muda.
Wacana ini langsung memantik perdebatan publik. Sebagian mendukung langkah pemerintah untuk menjaga moral dan mental anak muda, namun banyak juga yang menilai kebijakan tersebut terlalu menyederhanakan masalah.
Sebab, menurut American Psychological Association (APA), hubungan antara game kekerasan dan perilaku agresif manusia sangat lemah dan tidak signifikan secara ilmiah. Faktor yang jauh lebih berpengaruh adalah lingkungan sosial, pola asuh, dan kesehatan mental individu.
Selain itu, dunia game kini telah berkembang menjadi industri kreatif dan olahraga digital (e-sport) yang bernilai miliaran rupiah. Banyak anak muda justru menemukan ruang aktualisasi, kerja tim, dan kreativitas melalui game. Menyalahkan game sepenuhnya tanpa melihat konteks sosial justru berpotensi mengaburkan akar masalah yang sebenarnya.
Fokus yang Sebenarnya: Lingkungan dan Dukungan Psikologis
Daripada berfokus pada pelarangan, yang lebih mendesak adalah membenahi sistem dukungan psikologis di sekolah.
Kasus bom rakitan di SMAN 72 menunjukkan bahwa masih ada celah besar dalam hal pendampingan mental bagi siswa yang mengalami tekanan.
Sekolah seharusnya menjadi tempat aman bagi remaja untuk berkembang dan berekspresi, bukan ruang yang menakutkan atau penuh tekanan. Guru, konselor, dan teman sebaya punya peran penting dalam menciptakan ekosistem yang empatik dan suportif.
Begitu pula dengan peran orang tua. Pengawasan bukan berarti pembatasan mutlak, melainkan pembicaraan terbuka tentang apa yang anak mainkan, tonton, dan rasakan. Literasi digital seharusnya menjadi pondasi utama, bukan sensor berlebihan.
Saatnya Mendengar, Bukan Menyalahkan
Baik kasus bom di sekolah maupun wacana pembatasan game perang sesungguhnya berakar pada satu hal: rasa tidak didengar dari generasi muda.
Anak-anak muda hari ini hidup di dunia yang penuh tekanan — akademik, sosial, hingga digital. Namun ketika tak ada ruang untuk menyalurkan perasaan itu, mereka bisa melampiaskan dengan cara yang ekstrem.
Daripada menuding teknologi atau game, mungkin sudah saatnya kita bertanya:
“Apakah kita benar-benar sudah mendengarkan mereka?”
Kesimpulan
Kasus bom rakitan di SMAN 72 bukan hanya soal keamanan, tapi juga cerminan krisis empati dan komunikasi di kalangan kita.
Game bukan musuh utama — ia hanyalah cermin dari dunia yang sedang berubah cepat.
Yang dibutuhkan bukan pelarangan, tapi pendidikan emosional dan dukungan sosial agar generasi muda bisa tumbuh dengan sehat, sadar, dan berdaya.
Baca juga: Ketika Hidup Terasa Seperti Zero-Sum Game