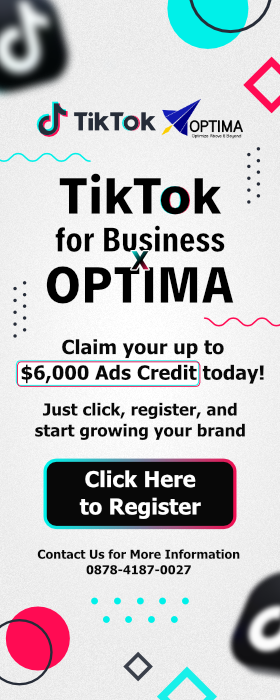CampusNet – Bencana seharusnya menjadi momen paling sunyi bagi kesombongan kekuasaan. Saat alam menunjukkan amarahnya, yang dibutuhkan bukan panggung, slogan, atau kamera — melainkan kehadiran yang tulus, empati yang nyata, dan tindakan yang konkret. Namun yang belakangan terlihat justru sebaliknya: di tengah lumpur, puing, dan tangis korban, sebagian pejabat hadir bukan sebagai penolong, melainkan sebagai figur yang sibuk menjaga citranya sendiri.
Fenomena ini memunculkan satu pertanyaan besar di tengah masyarakat: ke mana perginya empati para pemimpin di saat rakyat paling membutuhkan mereka?
Ketika Tragedi Diubah Menjadi Konten dan Simbol
Beberapa pernyataan dan tindakan di lokasi bencana menimbulkan kegelisahan publik. Kalimat-kalimat yang terdengar meremehkan, pembelaan yang mengaburkan persoalan lingkungan, hingga gestur simbolik yang terlalu dramatis memperlihatkan satu pola yang berulang: tragedi diperlakukan sebagai latar pencitraan.
Alih-alih fokus pada keselamatan, evakuasi, dan pemulihan korban, perhatian justru terserap pada bagaimana seorang pejabat terlihat di kamera, apa yang ia kenakan, dan bagaimana momen itu akan tersebar di media sosial. Penderitaan berubah menjadi properti visual. Luka menjadi latar foto. Di titik ini, empati kehilangan makna kemanusiaannya dan menjelma menjadi strategi komunikasi politik.
Ucapan yang Tidak Peka Lebih Menyakitkan dari Banjir Itu Sendiri
Bagi korban, kehilangan rumah, keluarga, dan rasa aman bukanlah drama sehari dua hari. Itu trauma jangka panjang. Maka ketika yang terdengar justru ucapan-ucapan tidak relevan, bahkan bernuansa politis, luka itu terasa berlipat ganda. Bukan hanya karena bencana alam, tetapi karena dikhianati oleh rasa kemanusiaan dari mereka yang seharusnya melindungi.
Pada momentum seperti inilah, kata-kata bukan sekadar rangkaian kalimat. Kata-kata adalah bentuk sikap. Dan ketika sikap itu menunjukkan ketidakpedulian, maka yang sedang dipertaruhkan bukan hanya reputasi pejabat — tetapi kepercayaan publik.
Masalah Utamanya: Citra Mengalahkan Nurani
Ironisnya, para pejabat itu bukan tidak tahu situasi sebenarnya. Mereka memiliki akses pada data, laporan lapangan, tim ahli, hingga perangkat negara yang lengkap. Namun sebagian memilih versi realitas yang paling menguntungkan citra pribadi mereka. Yang dipikirkan bukan lagi “apa yang bisa saya lakukan,” melainkan “bagaimana saya terlihat.”
Di sinilah akar persoalan itu tumbuh. Ketika kekuasaan kehilangan rasa malu, maka empati menjadi korban berikutnya. Dan ketika empati mati, maka tak ada lagi perbedaan antara pemimpin dan penonton.
Kita Tidak Kekurangan Pemimpin Pintar, Tapi Kekurangan yang Peduli
Negeri ini dipenuhi orang-orang cerdas di kursi kekuasaan. Namun kecerdasan tanpa empati hanya melahirkan keputusan dingin yang jauh dari rasa keadilan. Bencana bukan hanya soal infrastruktur yang runtuh, tetapi juga tentang retaknya hubungan antara pemimpin dan rakyatnya.
Sudah saatnya kita berhenti mengagungkan pejabat yang pandai berbicara tapi gagal merasa. Sebab dalam situasi genting, rakyat tidak membutuhkan kata-kata indah, tidak membutuhkan gaya heroik, dan tidak membutuhkan simbol perlawanan palsu. Yang dibutuhkan hanya satu hal: manusia yang peduli pada manusia lainnya.
Jika seorang pejabat tidak mampu menunjukkan itu, maka sesungguhnya ia bukan hanya gagal menjalankan tugasnya — ia telah gagal sebagai manusia.
Dan ketika itu dibiarkan terus terjadi, jangan heran jika suatu hari nanti kita sadar:
yang menjadi bencana terbesar di negeri ini bukanlah alam, melainkan mereka yang kehilangan empati saat memegang kekuasaan.
Baca juga: Gajah Sumatra Terancam Punah di Tesso Nilo: Krisis Ekologi yang Diabaikan Negara