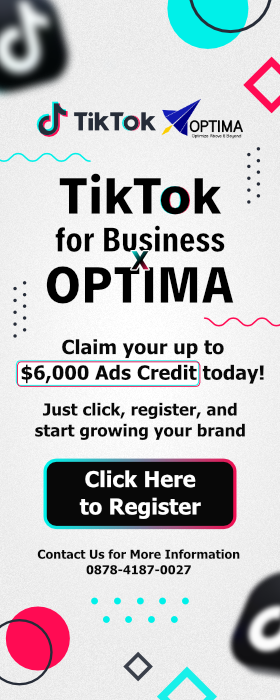CampusNet – Bencana seharusnya menjadi ruang paling suci bagi kemanusiaan. Namun belakangan, ruang itu berubah menjadi ajang kompetisi citra. Bukannya berlomba-lomba membantu warga yang kehilangan rumah, harta, bahkan keluarga, beberapa pejabat justru berebut spotlight dan merasa tersaingi oleh relawan yang bergerak lebih cepat.
Kasus terbaru memperlihatkan bagaimana seorang anggota DPR mengomentari donasi besar dari relawan Ferry Irwandi untuk korban bencana di Aceh dan Sumatra—dengan nada meremehkan. Alih-alih berterima kasih, ia justru membandingkan sumbangan itu dengan “triliunan” yang diklaim berasal dari negara, padahal itu merupakan kewajiban negara. Publik pun sepakat: komentar seperti ini bukan hanya tidak sensitif, tapi menunjukkan betapa rapuhnya ego sebagian pejabat kita.
1. Ketika Kekuasaan Melahirkan Generasi Pemimpin Camera-Addicted
Budaya politik kita telah melahirkan pejabat yang camera-ready, bukan crisis-ready.
Yang penting tampil dulu, kerja belakangan. Yang penting viral dulu, dampak belakangan.
Empati tak lagi menjadi kompetensi. Citra-lah yang menggerakkan tatanan.
Dan inilah masalahnya: kamera selalu jujur, tapi pejabat justru terlalu sibuk menjaga “angle” agar tetap terlihat heroik. Sementara relawan yang nyata-nyata bekerja dianggap mengambil panggung.
Sindrom Narsistik: Tak Tahan Lihat Orang Lain Dipuji
Ciri paling kasat mata dari perilaku yang mirip NPD (narcissistic traits):
mudah tersinggung ketika ada orang lain yang terlihat lebih baik.
Relawan donasi miliaran?
Ancaman.
Bantuan cepat dari komunitas?
Gangguan citra.
Publik lebih percaya pada warga biasa?
Cedera ego.
Padahal rakyat tidak peduli siapa yang lebih terlihat. Yang mereka butuhkan hanya: air bersih, logistik, akses kesehatan, dan rasa aman.
Jika sebuah donasi besar membuat pejabat panas dingin, itu tanda bahwa masalahnya bukan pada relawan—tapi pada ego kekuasaan yang rapuh.
Jauh dari Lapangan, Dekat dengan Mikrofon
Di banyak daerah bencana, warga harus menunggu berjam-jam untuk bantuan pertama. Tapi di ruang ber-AC, ada pejabat yang justru menghitung-hitung angka dan membandingkan siapa paling berjasa.
Ironinya?
Yang paling teriak “negara sudah hadir!” sering kali adalah mereka yang paling jauh dari lokasi kejadian.
Ketika tragedi hanya dilihat lewat laporan staf, empati tak pernah tumbuh.
Karena untuk merasakan penderitaan, seseorang harus hadir, bukan sekadar hadir di live streaming.
Medsos Mengubah Pejabat Menjadi Influencer yang Gagal
Setiap tragedi kini memiliki satu pola yang menjemukan:
kamera datang duluan, pejabat belakangan.
Kunjungan beberapa menit di lokasi bencana disulap menjadi konten dramatis. Caption panjang, wajah serius, dan beberapa potret “menghibur korban” jadi bagian dari strategi branding yang dipoles rapi.
Sementara relawan yang bekerja sepanjang malam?
Tidak ada kamera yang meliput, maka bagi sebagian pejabat, seolah-olah itu tidak terjadi.
Media sosial telah memaksa pejabat untuk tampil sempurna, bahkan ketika rakyat sedang bertahan hidup dalam ketidakpastian.
Ketika Bencana Dijadikan Arena Kompetisi: Siapa yang Lebih Hebat?
Ini puncak ironi kita hari ini:
Korban bencana membutuhkan bantuan,
tapi pejabat ribut soal siapa yang tampil lebih baik.
Bantuan relawan dianggap memalukan negara.
Solidaritas masyarakat dianggap mengganggu citra pemerintah.
Padahal sesederhana ini: dalam situasi darurat, semua tangan diperlukan, tanpa kecuali.
Jika seorang pejabat merasa tersaingi oleh warga yang membantu korban, itu bukan masalah relawan—itu masalah mentalitas pemimpinnya.
Penutup: Ego Tidak Menyelamatkan Nyawa
Bencana bukan panggung.
Pemimpin bukan selebritas.
Dan bantuan bukan kompetisi.
Selama pejabat lebih sibuk memoles citra daripada membangun empati, rakyat akan terus melihat wajah asli kekuasaan: rapuh, reaktif, dan jauh dari realitas.
Masyarakat tidak berharap pejabat sempurna.
Yang mereka butuhkan hanya satu:
pemimpin yang hatinya lebih besar dari kameranya.
Baca juga: Mengapa Pemerintah Enggan Menetapkan Banjir dan Longsor di Sumatra sebagai Bencana Nasional?