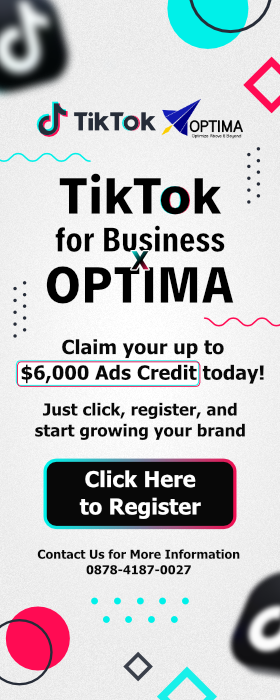CampusNet – Tiga hari terakhir, publik ramai dengan kasus aparat berseragam yang menyambangi pedagang penjual es gabus. Konon katanya, mereka datang sebagai tindak lanjut laporan call center 110 yang menuduh pedagang tersebut menjual es yang terbuat dari spons cuci piring. Meskipun tidak terbukti, kasus ini terlanjur viral akibat rekaman tuduhan dan kasarnya polisi terhadap pedagang tersebut.
Hal tersebut menjadi salah satu contoh nyata fenomena vigilantisme digital. Kamera tidak lagi menjadi alat dokumentasi, melainkan dapat menjadi senjata mengeksekusi reputasi orang lain tanpa bukti. Trial tidak terjadi di ruang persidangan dengan berbagai bukti konkret, melainkan di dunia maya berbukti video asal jepret. Bagaimana vigilantisme digital bekerja?
“Keadilan Instan” akibat Vigilantisme Digital
Kasus ini bermula dari laporan salah satu warga yang mencurigai barang dagangan Suderajat, yaitu es gabus, mengandung material spons. Tim piket Reskrim Polsek Kemayoran pun menindaklanjuti laporan tersebut dengan mendatangi Suderajat. Namun, ketika sidak tersebut, terlihat polisi sedang menginterogasinya dengan kasar. Aparat seperti mempermalukan Suderajat dengan memintanya memakan barang tersebut juga merusak dagangannya.
Video rekaman tersebut viral dan menjadi bahan perbincangan. Opini di kolom komentar terbagi dua. Di satu sisi, terdapat publik yang mengapresiasi kecepatan respons aparat. Di sisi lain, publik mengecam tindakan aparat yang mereka nilai terlalu kasar dan terburu-buru dalam “menghukum” tindakan tersebut.
Namun yang pasti, publik telah memberikan vonisnya. Suderajat mengaku mendapatkan penganiayaan ketika ada anak dari oknum polisi yang membeli dagangannya, “Bapaknya polisi, saya belum tahu. Dibejek-bejek, es kuenya saya. Terus es kue saya dilempar ke muka saya. Saya ditendang, dikepret, ditonjok,” ujarnya, melansir dari Tribunnews, Selasa (27/1).
Prosedur Hukum vs Vigilantisme Digital
Prosedur hukum ideal menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah bagi setiap warga. Namun, adanya vigilantisme digital menyebabkan viralitas seolah-olah lebih utama daripada fakta hukum yang sah. Alhasil, banyak orang menuduh tanpa menunggu uji lab dan kesaksian ahli demi validasi digital yang cepat. Sebaliknya, oknum pencari keadilan wajib mengikuti aturan main yang terukur. Akhirnya, opini pribadi yang dangkal sering kali mendahului proses hukum formal.
Selanjutnya, fenomena ini mengubah tujuan utama penegakan hukum di tengah masyarakat. Bukannya mencari kebenaran, pelaku vigilantisme digital justru mengejar angka dan engagement media sosial. Lebih jauh, hal tersebut dapat menjadi pemicu pembunuhan karakter yang bersifat permanen. Oleh karena itu, netizen perlu mewaspadai dampak buruk dari penghakiman massa di dunia nyata agar tidak menjadi salah satu penyebab “main hakim duluan”.
Dampak Psikososial dan Jejak Maya
Hasil lab forensik menyatakan barang dagangan Suderajat bebas dari kandungan berbahaya. Suderajat sudah terbukti tidak bersalah. Namun, video sidak tersebut akan ada di internet selamanya. Sulit untuk ia membersihkan nama baiknya di media sosial yang begitu luasnya.
Keadilan tidak bisa lahir dari amarah yang tertuang dalam kolom komentar. Jangan sampai demi satu konten “pahlawan”, kita sampai rela menghancurkan piring nasi orang yang jujur. Sebelum mengunggah sesuatu, tanyakan pada nuranimu; Ini bentuk menyuarakan keadilan, ataukah hanya aksi yang haus akan perhatian?
Baca juga: Mahasiswi Universitas Muhammadiyah Malang Tewas Dibunuh Polisi yang Merupakan Kakak Ipar