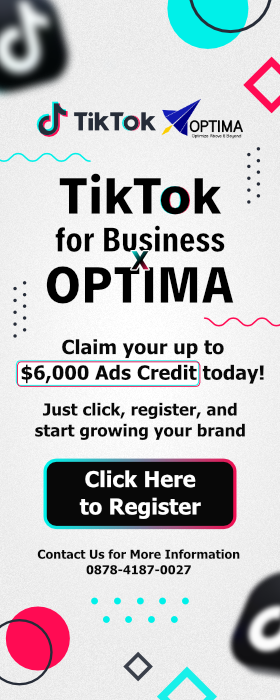CampusNet – Nama Adies Kadir sempat menjadi sorotan publik bukan karena terobosan legislasi, melainkan karena pernyataannya soal tunjangan rumah anggota DPR. Pernyataan itu dianggap membingungkan, tidak sensitif, dan jauh dari realitas ekonomi sebagian besar masyarakat. Meski kemudian diralat dan dinyatakan tidak melanggar kode etik, jejaknya telanjur tertanam dalam ingatan publik.
Di sinilah persoalan dimulai.
Publik tidak bekerja seperti lembaga. Klarifikasi dan putusan etik internal tidak serta-merta menghapus persepsi sosial. Dalam isu yang menyentuh kesejahteraan rakyat, cara bicara elite sering kali lebih menentukan kepercayaan dibandingkan prosedur yang rapi.
Tak lama setelah kontroversi itu mereda, publik dihadapkan pada keputusan lain: Adies Kadir diangkat menjadi hakim Mahkamah Konstitusi. Secara hukum, proses ini sah. Secara prosedural, kewenangan DPR untuk mengusulkan hakim MK tidak dapat diperdebatkan. Namun demokrasi tidak hanya berdiri di atas legalitas, melainkan juga legitimasi etik.
Mahkamah Konstitusi bukan lembaga biasa. Ia adalah penjaga terakhir konstitusi, pengadil sengketa kekuasaan, dan benteng ketika proses politik kehilangan arah. Karena itu, figur yang duduk di dalamnya tidak hanya dituntut cakap secara hukum, tetapi juga memiliki jarak simbolik dari kepentingan politik praktis. Di sinilah kegelisahan publik menemukan relevansinya.
Pengangkatan tersebut terjadi di saat perhatian publik sedang buyar. Isu datang silih berganti, ruang diskusi cepat bergeser, dan sorotan media tidak lagi setajam sebelumnya. Dalam kondisi seperti ini, keputusan besar sering kali lolos dari perdebatan mendalam. Bukan karena publik setuju, melainkan karena energi kolektif telah terpecah.
Pola ini bukan hal baru. Kontroversi muncul, waktu berjalan, sorotan mereda, lalu jabatan baru datang. Di titik ini, banyak orang mulai melihat kerja oligarki politik—bukan sebagai konspirasi gelap, melainkan sebagai rutinitas kekuasaan yang sah secara aturan, namun miskin refleksi etik. Kekuasaan berputar di lingkar yang sama, dengan aktor yang saling mengenal dan saling mengamankan.
Oligarki tidak selalu membungkam kritik. Ia cukup menunggu. Waktu menjadi alat paling efektif untuk menormalkan kontroversi. Ketika publik lelah, sistem tetap berjalan. Dan ketika keputusan diambil tanpa tekanan sosial yang kuat, etika sering kali menjadi pertimbangan terakhir.
Masalahnya, dampak dari pola ini tidak berhenti pada satu nama. Yang terkikis adalah kepercayaan terhadap lembaga. Ketika figur dengan rekam kontroversi komunikasi publik tetap melaju ke posisi konstitusional, pesan yang sampai ke masyarakat sederhana: prosedur lebih penting daripada keteladanan.
Demokrasi memang membutuhkan aturan agar tidak runtuh. Namun tanpa etika, ia kehilangan arah. Konstitusi tetap dibaca, putusan tetap diketuk, tetapi wibawa moral lembaga perlahan memudar. Dan ketika publik mulai terbiasa dengan jarak antara kekuasaan dan nilai, krisis yang sesungguhnya telah terjadi.
Pada akhirnya, pertanyaannya bukan apakah pengangkatan itu sah, melainkan apa arti sah jika kepercayaan terus terkikis. Di situlah demokrasi diuji—bukan di meja prosedur, tetapi di mata warganya.