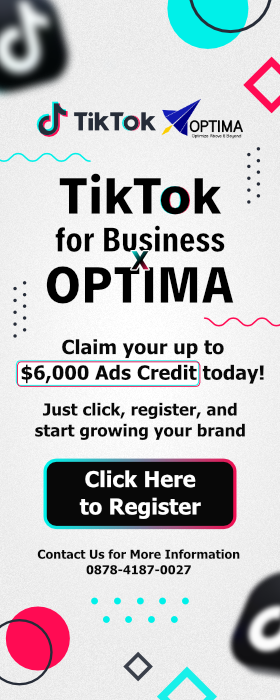CampusNet – Istilah perdamaian kerap terdengar netral, bahkan mulia. Namun dalam praktik politik global, kata ini sering kali menjadi payung bagi keputusan-keputusan yang justru mengaburkan persoalan utama: keadilan dan kedaulatan. Board of Peace, badan internasional yang digagas Amerika Serikat untuk mengatur stabilisasi dan rekonstruksi Gaza, adalah contoh terbaru dari paradoks tersebut.
Forum ini diklaim sebagai upaya internasional untuk menciptakan ketertiban pascaperang. Namun sejak awal, Board of Peace menuai kritik mendasar: Palestina tidak dilibatkan sebagai aktor politik utama dalam penentuan masa depan Gaza. Perdamaian dibicarakan tanpa kehadiran penuh pihak yang wilayahnya dihancurkan dan rakyatnya menjadi korban utama.
Lebih problematis lagi, forum ini dipimpin oleh Amerika Serikat—negara yang secara konsisten menjadi pendukung politik, militer, dan diplomatik Israel. Dukungan tersebut terus berlangsung bahkan di tengah tuduhan luas terhadap Israel atas kejahatan perang dan pelanggaran hukum humaniter internasional di Gaza.
Dalam konteks inilah keputusan Indonesia untuk turut serta dalam Board of Peace memunculkan tanda tanya besar.
Perdamaian Tanpa Palestina
Struktur Board of Peace menempatkan Palestina bukan sebagai subjek politik berdaulat, melainkan sebagai entitas administratif yang menjalankan fungsi teknis. Tidak ada kursi penentu kebijakan bagi representasi politik Palestina yang sah. Dengan kata lain, masa depan Gaza dirancang oleh aktor eksternal, sementara rakyat Palestina ditempatkan sebagai objek kebijakan.
Pendekatan semacam ini bertentangan dengan prinsip self-determination, salah satu pilar hukum internasional yang menyatakan bahwa setiap bangsa berhak menentukan nasib politiknya sendiri. Tanpa prinsip ini, perdamaian kehilangan legitimasi moral dan politik sejak awal.
Amerika dan Bias Kepemimpinan Perdamaian
Fakta bahwa Board of Peace dipimpin Amerika tidak dapat dilepaskan dari rekam jejak negara tersebut dalam konflik Palestina–Israel. Amerika bukan aktor netral. Ia adalah pemasok senjata, pelindung diplomatik di Dewan Keamanan PBB, dan sekutu strategis utama Israel.
Ketika negara dengan posisi seberat itu memimpin forum “perdamaian”, maka wajar jika publik mempertanyakan: perdamaian untuk siapa, dan dengan definisi siapa?
Forum ini berisiko menggeser konflik dari isu pendudukan dan keadilan politik menjadi semata persoalan manajemen keamanan dan rekonstruksi ekonomi. Akar konflik diredam, sementara dampaknya dikelola.
Indonesia Turut Serta, dengan Biaya
Keputusan Indonesia untuk bergabung tidak hanya bersifat simbolik. Indonesia dikabarkan harus membayar kontribusi sebesar US$1 juta untuk menjadi bagian dari Board of Peace. Angka ini bukan sekadar biaya administratif, melainkan bentuk komitmen politik dan legitimasi terhadap forum tersebut.
Pertanyaan yang kemudian muncul bukan soal mampu atau tidaknya Indonesia membayar, melainkan: untuk apa legitimasi itu diberikan? Apakah dana dan partisipasi tersebut digunakan untuk memperjuangkan kemerdekaan Palestina, atau justru memperhalus citra sebuah forum yang menyingkirkan Palestina dari proses politik utama?
UUD 1945 sebagai Tolak Ukur
Pembukaan UUD 1945 alinea pertama secara tegas menyatakan bahwa:
“Kemerdekaan ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan.”
Rumusan ini bukan sekadar teks historis, melainkan dasar normatif kebijakan luar negeri Indonesia. Selama puluhan tahun, prinsip ini menjadi alasan konsisten Indonesia mendukung Palestina dan menolak segala bentuk normalisasi dengan Israel.
Ketika Indonesia kini turut serta dalam forum internasional yang membahas masa depan wilayah Palestina tanpa melibatkan Palestina sebagai subjek politik, maka relevansi prinsip konstitusional tersebut layak dipertanyakan.
Jarak Negara dan Rakyat
Di dalam negeri, solidaritas rakyat Indonesia terhadap Palestina tidak pernah surut. Boikot produk, aksi massa, dan tekanan publik mencerminkan kesadaran kolektif yang tumbuh dari nilai konstitusional dan kemanusiaan. Solidaritas ini bukan sekadar emosi, melainkan sikap politik warga negara.
Namun keputusan untuk bergabung dengan Board of Peace justru menciptakan jarak antara sikap negara dan aspirasi rakyat. Ketika negara bergerak dalam kerangka pragmatisme diplomatik, publik melihat adanya pengaburan prinsip yang selama ini dijunjung.
Perdamaian dan Risiko Legitimasi
Dengan turut sertanya Indonesia, Board of Peace memperoleh legitimasi tambahan, terutama karena Indonesia dikenal sebagai negara dengan citra kuat pro-Palestina. Kehadiran Indonesia dapat digunakan untuk menetralkan kritik internasional terhadap struktur forum tersebut.
Alih-alih mengubah arah kebijakan, Indonesia justru berisiko menjadi penutup wajah dari proses perdamaian yang timpang.
Pertanyaan yang Tidak Bisa Dihindari
Perdamaian sejati tidak hanya diukur dari stabilitas keamanan atau masuknya investasi, tetapi dari keadilan politik dan pengakuan terhadap kedaulatan rakyat yang dijajah. Jika Palestina tidak diberi ruang menentukan masa depannya sendiri, maka perdamaian yang dibangun hanyalah administrasi konflik, bukan penyelesaian.
Keputusan Indonesia untuk turut serta—bahkan dengan membayar US$1 juta—perlu diuji secara terbuka: apakah langkah ini masih setia pada amanat UUD 1945, atau justru menandai pergeseran prinsip demi kepentingan diplomatik jangka pendek?
Pertanyaan ini penting, bukan untuk melemahkan posisi Indonesia di dunia internasional, tetapi justru untuk memastikan bahwa setiap langkah diplomasi tetap berpijak pada konstitusi dan keadilan.