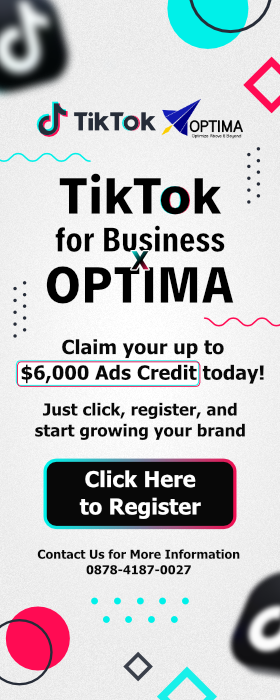CampusNet – Belum genap dua tahun pemerintahan berjalan, tetapi wacana “Prabowo dua periode” sudah mulai digaungkan secara terbuka oleh sejumlah elite politik. Pernyataan itu tidak lagi datang dari sekadar relawan akar rumput, melainkan dari pimpinan partai dan tokoh koalisi pemerintahan. Secara hukum, tentu tidak ada yang keliru. Konstitusi membolehkan presiden menjabat maksimal dua periode. Namun demokrasi bukan hanya soal apa yang diperbolehkan, melainkan juga soal apa yang pantas dibicarakan dalam konteks dan waktu yang tepat.
Periode kedua dalam sistem demokrasi idealnya merupakan hasil evaluasi publik terhadap kinerja periode pertama. Ia adalah konsekuensi dari rekam jejak yang telah teruji, bukan agenda yang dipromosikan ketika masa jabatan bahkan belum mencapai titik pertengahan. Ketika pembicaraan tentang 2029 muncul sebelum rapor pemerintahan benar-benar dinilai, publik wajar bertanya: apakah evaluasi sudah cukup, atau konsolidasi kekuasaan bergerak lebih cepat daripada akuntabilitas?
Sejumlah elite telah memberi sinyal dukungan tersebut. Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar menyebut keberlanjutan kepemimpinan penting untuk memastikan kesinambungan program. Partai Golkar melalui Airlangga Hartarto menyatakan kesiapan mendukung kembali Prabowo jika maju pada 2029. NasDem menyebut wacana dua periode sebagai hal yang wajar dalam demokrasi. Gerindra sebagai partai presiden tentu menjadi poros utama dukungan, bersama partai-partai koalisi lain seperti PAN dan PKB.
Konfigurasi ini membentuk koalisi yang luas di parlemen. Dalam sistem presidensial multipartai seperti Indonesia, koalisi besar memang menjanjikan stabilitas pemerintahan. Dukungan mayoritas memudahkan proses legislasi dan meminimalkan kebuntuan politik. Namun stabilitas yang terlalu dominan juga memiliki sisi lain: berkurangnya daya tekan oposisi formal.
Di sinilah sensitivitas publik menemukan konteksnya. Ketika oposisi parlemen menyusut dan sebagian besar partai berada dalam barisan pemerintahan, wacana Prabowo dua periode menjadi lebih dari sekadar ekspresi optimisme politik. Ia menjadi simbol konsolidasi dini. Dalam situasi di mana keseimbangan kekuasaan sudah cenderung berat ke satu sisi, pembicaraan tentang perpanjangan mandat terasa seperti penguatan dominasi sebelum evaluasi tuntas.
Tentu saja, tidak ada yang salah dengan keberlanjutan program. Banyak kebijakan publik membutuhkan waktu panjang untuk menunjukkan hasil. Stabilitas kepemimpinan sering dianggap penting untuk memastikan kesinambungan pembangunan. Namun keberlanjutan dalam demokrasi harus lahir dari legitimasi yang diperbarui melalui proses yang kompetitif dan terbuka—bukan dari konsensus elite yang terbentuk terlalu cepat.
Demokrasi yang matang memahami bahwa kekuasaan selalu membutuhkan jarak dari ambisi. Waktu memberi ruang bagi publik untuk menilai, membandingkan, dan mempertimbangkan alternatif. Ketika elite mulai mengunci horizon politik jauh sebelum masa jabatan memasuki fase evaluasi yang substansial, ruang refleksi publik berisiko menyempit.
Wacana Prabowo dua periode juga membawa dimensi simbolik yang kuat. Ia mengirim pesan bahwa kepemimpinan saat ini telah cukup percaya diri untuk melanjutkan. Namun kepercayaan diri kekuasaan tidak selalu identik dengan kepercayaan publik. Legitimasinya baru benar-benar kokoh jika lahir dari pengakuan luas atas capaian yang konkret dan terukur.
Indonesia tidak sedang berada dalam krisis demokrasi. Ruang kritik masih terbuka, pemilu tetap berjalan, dan mekanisme konstitusional tetap berlaku. Namun kualitas demokrasi tidak hanya diukur dari prosedur formal. Ia juga ditentukan oleh sensitivitas terhadap keseimbangan kekuasaan dan kesediaan untuk menempatkan evaluasi di atas ambisi.
Dalam konteks ini, wacana dua periode bukan semata isu elektoral. Ia adalah cermin bagaimana elite memandang relasi antara kekuasaan dan waktu. Apakah waktu digunakan untuk membuktikan kinerja terlebih dahulu, atau untuk mengamankan masa depan politik sedini mungkin?
Sejarah demokrasi menunjukkan bahwa mandat kedua yang kuat selalu lahir dari pembuktian, bukan perencanaan dini. Ketika periode pertama benar-benar menghasilkan capaian yang diakui luas, pembicaraan tentang keberlanjutan akan muncul secara organik dari publik—bukan harus digerakkan dari atas.
Belum setengah jalan, tetapi pembicaraan sudah melompat jauh ke depan. Dalam politik, mungkin itu strategi. Namun dalam demokrasi, strategi tetap harus tunduk pada etika waktu.
Karena pada akhirnya, periode kedua bukan sekadar soal kesempatan. Ia adalah soal kelayakan yang dibuktikan.
Dan kelayakan tidak ditentukan oleh seberapa cepat ia dibicarakan, melainkan seberapa matang ia dipertanggungjawabkan.