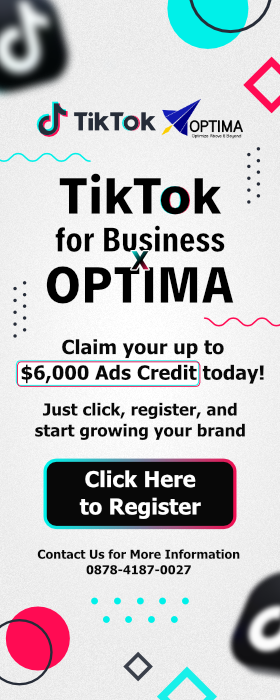CampusNet – Di negeri yang saban minggu diberi “kejutan” banjir, longsor, atau gempa, publik seharusnya sudah kebal terhadap drama pencitraan pejabat. Tapi faktanya? Mereka masih laku. Masih dipuji. Masih dianggap “peduli.”
Dan para pejabat? Mereka tahu itu. Mereka baca polanya. Mereka manfaatkan.
Ada alasan mengapa pejabat yang minim empati, narsistik, dan sibuk berebut sorotan kamera terus bermunculan: karena selalu ada pasar yang menyambutnya dengan tangan terbuka.
Ketika Pencitraan Menang dari Kepedulian
Setiap kali bencana terjadi, rakyat panik, relawan turun, dan pejabat… ya, pejabat turun juga—bersama tim dokumentasi.
Ada momen-momen absurd yang terus berulang:
- Pejabat datang terlambat tapi minta adegan “pengarahan” diulang sekali lagi.
- Bantuan diserahkan, tapi kamera harus dapat angle yang “heroik.”
- Warga sedang trauma, tapi tetap diminta senyum untuk konten.
Apakah publik marah? Ada yang marah. Tapi banyak juga yang justru berkomentar:
“Yang penting turun, daripada nggak sama sekali.”
Inilah masalahnya: standar kita terlalu rendah.
Mengapa Pejabat Minim Empati Masih Eksis?
Karena perilaku mereka… berfungsi.
Bukan bagi masyarakat, tapi bagi reputasi mereka.
1. Publik Masih Menghargai Simbol, Bukan Substansi
Pejabat cukup datang, pegang sekantong mi instan, tersenyum, dan publik merasa sudah cukup.
Tidak perlu kebijakan, tidak perlu konsistensi, tidak perlu strategi jangka panjang.
“Yang penting kelihatan peduli.”
2. Media Sosial Membentuk Persepsi Cepat—dan Dangkal
Video 15 detik lebih mudah diterima daripada laporan aksi nyata yang butuh waktu untuk terasa dampaknya.
3. Banyak Rakyat Merasa Tak Punya Pilihan
Mereka sudah terbiasa kecewa.
Ketika pejabat datang ke lokasi bencana, walaupun hanya 10 menit, itu masih terasa seperti “bantuan.”
Padahal sesungguhnya: itu hanya konten.
NPD di Pemerintahan: Ketika Kekuasaan Bertemu Kehausan Validasi
Ciri-cirinya terlihat jelas:
- Merasa harus menjadi pusat perhatian di tengah tragedi.
- Iri jika ada relawan yang bergerak lebih cepat atau lebih efektif.
- Tidak tahan jika bukan mereka yang dipuji publik.
- Membuat komentar-komentar defensif, bahkan agresif, ketika pencitraan mereka “tersaingi.”
Ketika pejabat merasa tersaingi oleh relawan yang tulus menggalang donasi, itu bukan sekadar salah bicara—itu gejala.
Publik Juga Punya Andil
Tidak enak mengakui ini, tapi harus:
selama masyarakat masih mengkonsumsi pencitraan, pejabat akan terus memproduksinya.
Yang membuat pejabat toxic terus berani adalah:
- like, share, dan komentar yang berlebihan,
- glorifikasi tindakan simbolis,
- dan rendahnya ekspektasi publik terhadap pemimpin.
Jika permintaan tidak berubah, penawarannya juga tidak.
Pencitraan Boleh, Tapi Empati Tidak Bisa Dipalsukan
Pencitraan bukan dosa. Semua pemimpin butuh membangun citra.
Yang menjadi masalah adalah ketika citra menjadi lebih penting daripada kerja nyata.
Ketika pencitraan mengorbankan martabat orang yang sedang menderita.
Bencana harusnya menjadi ruang solidaritas, bukan arena kompetisi ego.
Penutup: Tanggung Jawab Kita Bersama
Jika kita ingin pejabat yang benar-benar bekerja, bukan sekadar tampil, maka publik harus lebih cerdas dalam menilai:
Apakah ini bantuan atau konten?
Apakah ini kepedulian atau kehausan validasi?
Ketika publik berhenti kagum pada hal-hal dangkal, pejabat pun terpaksa berubah—karena pasar pencitraan mereka akhirnya bangkrut.
Baca juga: Sindrom Pencitraan Pejabat: Ketika Kamera Lebih Penting dari Korban Bencana