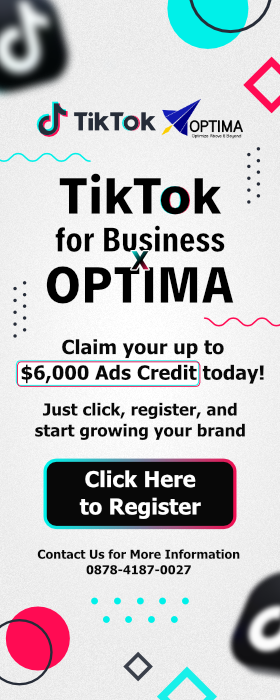CampusNet – Beberapa hari terakhir, banjir bandang dan longsor di beberapa daerah Sumatera menyapu rumah, menelan nyawa, dan memaksa ribuan orang tidur di lantai dingin pengungsian. Di Thailand dan Malaysia, air bah juga merajalela. Cuaca ekstrem makin gila. Tanah makin rapuh.
Tapi di tengah semua itu, seorang presiden pernah bilang:
“Tak perlu takut deforestasi.”
Kalimat yang terasa seperti tamparan, bukan ketenangan.
Karena yang sedang takut itu bukan rakyat yang “terlalu panik”.
Yang seharusnya takut justru mereka yang membiarkan hutan semakin botak.
Deforestasi Sudah Gila-Gilaan — Tapi Kita Disuruh Tenang?
Sulit memahami logika “nggak perlu takut”, ketika:
- Hutan Sumatera sudah seperti puzzle berantakan,
- Kalimantan bolong sana-sini karena tambang,
- Papua mulai diincar kapital besar,
- Dan Jakarta tiap tahun merayakan festival asap.
Tapi rakyat disuruh percaya bahwa semua baik-baik saja?
Rasanya seperti dokter yang bilang:
“Paru-paru Anda bolong, tapi nggak usah takut. Nikmati saja.”
Begitu absurdnya sampai mau ketawa pun nggak tega.
Narasi Penguasa Selalu Sama: Ketika Hutan Hilang, Salahkan Hujan
Setiap tahun, script-nya sama:
Banjir? Salah hujan.
Longsor? Salah topografi.
Asap? Salah angin.
Banjir bandang? Salah curah hujan ekstrem global.
Pokoknya semua salah—kecuali kebijakan.
Padahal kita tahu:
hujan memang dari langit,
tapi kebodohan yang membiarkan hutan rusak datangnya dari manusia.
Kita hidup di negara yang menganggap bencana itu “takdir”, bukan konsekuensi.
Sehingga solusinya selalu doa dan bantuan, bukan pembenahan akar masalah.
Pemimpin Takut Ekonomi Turun, Tapi Tidak Takut Rakyat Tenggelam
Pernyataan “tidak perlu takut deforestasi” muncul dari pola pikir yang berbahaya:
lebih takut kehilangan investor daripada kehilangan hutan.
Hutan yang dibiarkan hilang demi ekspansi industri, sawit, tambang, dan konsesi.
Karena keuntungan selalu terlihat,
sementara bencana dianggap “kejadian insidental”.
Padahal keuntungan ekonomi bisa dicetak ulang.
Nyawa tidak.
Masalah Sebenarnya Bukan Rakyat yang Takut — Tapi Pemerintah yang Nggak Mau Takut
Ketika masyarakat khawatir, itu tanda mereka masih punya akal sehat.
Karena bagaimanapun, melihat banjir bandang yang menyeret rumah itu menakutkan.
Melihat bukit runtuh dan menelan desa itu menakutkan.
Melihat anak-anak mengungsi dengan baju basah itu menakutkan.
Yang mengerikan adalah ketika pemimpin tidak takut pada hal-hal itu.
Tidak takut deforestasi = tidak takut kerusakan jangka panjang.
Tidak takut kerusakan = tidak takut bencana berulang.
Tidak takut bencana = tidak takut kehilangan rakyatnya sendiri.
Itu bukan keberanian. Itu ketiadaan empati.
Kalau Pemimpin Tetap Meremehkan, Alam Akan Mengajari dengan Caranya Sendiri
Alam tidak peduli pidato.
Tidak peduli klaim statistik.
Tidak peduli pencitraan.
Jika hutan terus hilang, ia hanya akan menjawab dengan satu bahasa:
banjir, longsor, badai, dan musim yang makin kacau.
Pemerintah boleh bilang kita tidak perlu takut.
Tapi kenyataan berkata lain.
Karena yang paling menakutkan dari deforestasi
bukan hanya hilangnya hutan.
Tapi hilangnya kewarasan pengambil keputusan.
Dan kalau itu yang hilang…
bencana bukan lagi ancaman —
tapi rutinitas.
Baca juga: Bencana yang Berulang, Kesalahan yang Sama: Saatnya Mengakui Akar Masalah Krisis Iklim di Indonesia