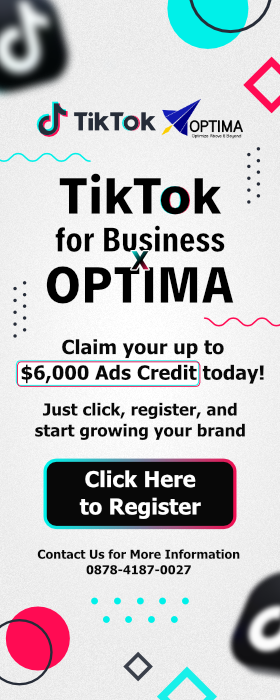CampusNet – Kasus demi kasus perundungan yang berujung kematian kembali muncul di hadapan kita. Setiap beberapa minggu, ada saja berita tentang siswa SMP atau SMA yang mengalami kekerasan fisik, tekanan psikologis, hingga akhirnya kehilangan nyawa. Nama korban sering kali berbeda, tetapi pola ceritanya sama: dimulai dari candaan yang dibiarkan, kekerasan yang dianggap wajar, laporan yang tak digubris, hingga tragedi yang membuat satu keluarga hancur dan satu sekolah dipenuhi rasa bersalah.
Fenomena ini bukan kejadian tunggal. Ini adalah pola. Dan ketika pola kekerasan mulai berulang, itu bukan lagi persoalan individu—tetapi kegagalan sistem.
Perundungan yang Dianggap Biasa, Dampak yang Luar Biasa
Masih banyak sekolah yang memandang bullying sebagai “dinamika pertemanan”, “kenakalan khas remaja”, atau “ujian mental agar mereka kuat”. Narasi ini berbahaya. Ia membuat kekerasan dinormalisasi dan korban menjadi makin tak terlihat.
Di balik satu tindakan mendorong, mengejek, atau memukul, ada efek berantai: harga diri anak runtuh, rasa aman hilang, dan kondisi mental memburuk. Di era media sosial, serangan tidak berhenti di halaman sekolah. Korban bisa dilecehkan 24 jam lewat chat, komentar, dan grup pertemanan. Ketika tekanan ini menumpuk, risiko depresi dan tindakan fatal menjadi sangat nyata.
Sayangnya, banyak kasus menunjukkan bahwa awal mula tragedi sebenarnya dapat dihentikan—jika ada satu guru yang peka, satu pihak sekolah yang responsif, atau satu sistem pelaporan yang bekerja.
Masalahnya Bukan Tidak Ada Aturan — Tapi Tidak Ada Budaya Perlindungan
Indonesia sebenarnya sudah memiliki regulasi terkait perlindungan anak. Namun kertas tidak bisa bekerja sendiri. Yang kurang adalah budaya perlindungan:
- ruang aman untuk melapor,
- guru yang dilatih mendeteksi tanda kekerasan,
- konselor yang cukup untuk menampung curhat anak,
- orang tua yang mau mendengar tanpa menghakimi,
- sekolah yang tidak buru-buru menutup kasus demi menjaga nama baik.
Banyak sekolah masih menganggap penyelesaian masalah adalah soal “mendamaikan pelaku dan korban” lalu memaksa mereka bersalaman. Ini bukan penyelesaian. Ini hanya menutup luka dengan perban tipis tanpa mengobati infeksinya.
Perundungan adalah kekerasan, bukan konflik kecil. Dan kekerasan tidak selesai dengan permintaan maaf formal di ruang BK.
Era Digital Membuat Luka Lebih Dalam
Jika dulu bullying berhenti ketika jam pelajaran selesai, kini tidak lagi.
Cyberbullying membuat teror mengikuti korban ke kamar tidur, ke dalam grup WhatsApp, ke komentar Instagram, bahkan ke gim yang mereka mainkan.
Di sini kita melihat masalah baru:
Teknologi berkembang lebih cepat daripada pendidikan karakter. Anak remaja memiliki perangkat, tetapi tidak memiliki kapasitas emosional dan etika digital yang matang.
Orang tua sering tidak menyadari apa yang terjadi di layar ponsel anak mereka. Sekolah sering merasa tidak punya kuasa mengatur ranah daring. Padahal, keduanya tetap terhubung erat. Ketika lingkungan digital tidak terkendali, kekerasan di dunia nyata akan ikut meningkat.
Kegagalan Penanganan: Kita Terlalu Lambat Bertindak
Hampir semua kasus perundungan yang berujung kematian memiliki satu benang merah: respons yang terlambat.
Laporan diabaikan. Tanda-tanda awal tidak dibaca. Intervensi baru dilakukan ketika kondisi korban sudah parah.
Ini bukan salah satu pihak saja.
Ini adalah kegagalan bersama: keluarga, sekolah, masyarakat, hingga negara.
Sekolah butuh SOP yang jelas, orang tua butuh literasi pengasuhan, negara perlu memperkuat layanan kesehatan mental remaja, dan platform digital punya tanggung jawab moral untuk mengamankan ruang publik yang digunakan anak-anak.
Inilah Saatnya Mengganti Paradigma: Dari Reaktif Menjadi Preventif
Jika kita hanya bereaksi saat ada anak yang meninggal, kita terlambat.
Pendidikan modern harus menggeser pendekatan menjadi preventif:
- Sekolah wajib punya mekanisme pelaporan anonim—bukan hanya kotak saran yang berdebu.
- Setiap guru harus dilatih membaca tanda kekerasan, sama pentingnya dengan pelatihan kurikulum.
- Konseling harus menjadi layanan utama, bukan pelengkap.
- Program literasi digital & empati wajib masuk kurikulum, bukan sekadar materi sisipan.
- Orang tua perlu terlibat lebih aktif, tidak menyerahkan seluruh pembinaan pada sekolah.
- Platform digital harus membangun ekosistem perlindungan anak, termasuk penghentian cepat konten bernada kekerasan.
Anak-anak punya hak untuk tumbuh, belajar, dan bermain tanpa rasa takut. Hak itu tidak boleh dipertaruhkan hanya karena sistem kita belum siap.
Tragedi Harus Berakhir di Sini
Setiap kali ada kasus perundungan yang berujung kematian, kita sering marah, sedih, dan menuntut perubahan. Tetapi setelah beberapa hari, isu reda dan kita kembali seperti biasa—sampai tragedi berikutnya muncul lagi.
Bullying bukan sekadar masalah remaja.
Ia adalah krisis moral, krisis pendidikan, dan krisis sosial.
Dan perubahan hanya akan terjadi jika sekolah, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan platform digital mengambil peran masing-masing—secara serius, konsisten, dan tanpa kompromi.
Anak yang hilang nyawanya tidak bisa kembali.
Tapi kita bisa memastikan tidak ada lagi anak lain yang harus bernasib sama.
Baca juga: Ketika Hidup Terasa Seperti Zero-Sum Game