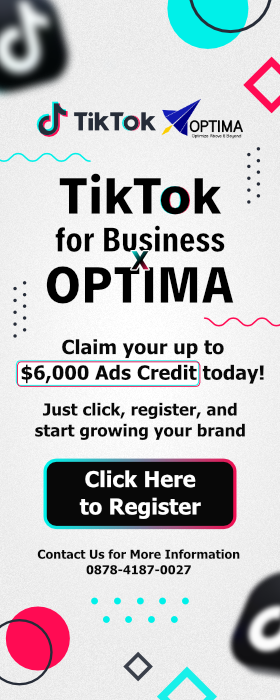CampusNet – Sumatra hari ini bukan sekadar pulau yang sering dilanda banjir dan longsor. Ia adalah arsip hidup kegagalan kebijakan lingkungan. Dalam beberapa dekade terakhir, hutan dibuka besar-besaran atas nama pembangunan—terutama untuk perkebunan sawit. Hasilnya bisa kita lihat sekarang: sungai meluap, tanah tak lagi menyerap air, dan bencana hidrometeorologi menjadi peristiwa rutin.
Ironisnya, alih-alih berhenti dan belajar, negara justru bersiap mengulang pola yang sama di wilayah lain. Kali ini, sasarannya adalah Tanah Papua.
Papua Bukan Lahan Kosong
Papua sering digambarkan sebagai wilayah luas yang “belum tergarap”. Framing ini berbahaya. Papua bukan ruang kosong di peta kebijakan, melainkan hutan tropis terakhir dan terluas di Asia Tenggara, sekaligus penjaga terakhir keanekaragaman hayati Nusantara.
Hutan Tanah Papua menyimpan tingkat keragaman hayati tertinggi di dunia:
lebih dari 20.000 spesies tanaman, 602 jenis burung, 125 mamalia, dan 223 reptil. Kehilangan hutan Papua bukan sekadar kehilangan pohon, tetapi runtuhnya satu sistem kehidupan utuh yang tidak bisa digantikan.
Penyangga Iklim dan Paru-Paru Dunia
Secara ekologis, hutan Papua berfungsi sebagai penyerap karbon alami yang sangat penting dalam menahan laju pemanasan global. Ia menjaga keseimbangan iklim regional dan global, sekaligus berperan sebagai penyangga air—menyerap hujan, menahan limpasan, dan mencegah banjir bandang.
Fungsi ini bukan teori. Sumatra telah membuktikan apa yang terjadi ketika hutan diganti oleh monokultur: tanah mengeras, daya serap air menurun drastis, dan setiap hujan ekstrem berubah menjadi bencana.
Sawit dan Kerusakan yang Terstruktur
Masalah utama bukan sekadar “pembangunan”, melainkan model pembangunan yang dipilih. Di Papua, yang didorong bukanlah pengelolaan hutan berbasis masyarakat atau agroforestri berkelanjutan, melainkan perkebunan sawit skala besar.
Sawit adalah tanaman monokultur yang:
- menghilangkan keanekaragaman hayati,
- merusak struktur tanah,
- menurunkan kemampuan penyerapan air,
- dan mengubah bentang alam hutan menjadi sistem produksi tunggal.
Di Sumatra dan Kalimantan, dampak ini sudah nyata. Maka ketika sawit diarahkan ke Papua, yang dipindahkan bukan sekadar investasi—melainkan risiko ekologis yang sudah terbukti merusak.
Dampak Sosial: Ketika Hutan Bukan Lagi Rumah
Bagi masyarakat adat Papua, hutan bukan komoditas. Ia adalah sumber hidup, sumber pangan, sumber obat, dan ruang spiritual yang diyakini sebagai Ibu Tanah Papua.
Riset Tumbuhan Obat dan Jamu (RISTOJA) 2017 mencatat 983 jenis tumbuhan obat di Papua, dengan 529 di antaranya terbukti berkhasiat secara medis. Ini menunjukkan bahwa hutan Papua juga menyimpan nilai ekonomi—tetapi ekonomi berbasis pengetahuan lokal dan keberlanjutan, bukan eksploitasi jangka pendek.
Ketika hutan digantikan sawit, yang hilang bukan hanya ekosistem, tetapi juga kemandirian dan identitas masyarakat adat.
Ancaman yang Sudah Terlihat
Forest Watch Indonesia mencatat bahwa hingga 2018, luas hutan alam yang tersisa di Tanah Papua sekitar 32,2 juta hektare. Angka ini memang masih besar, tetapi justru itulah yang membuatnya rawan: besar, menarik, dan dianggap siap dikorbankan.
Tanpa peninjauan ulang izin konsesi, tanpa pemetaan wilayah adat yang kuat, dan tanpa pengawasan yang serius, Papua berada di jalur yang sama dengan Sumatra—hanya berbeda waktu.
Sumatra Adalah Peringatan, Bukan Blueprint
Sumatra seharusnya menjadi peringatan keras bahwa sawit bukan solusi netral. Ia membawa keuntungan ekonomi bagi segelintir pihak, tetapi meninggalkan biaya ekologis dan sosial jangka panjang bagi publik.
Mengulang model sawit di Papua berarti mengabaikan seluruh pelajaran tersebut. Ini bukan ketidaktahuan, melainkan pilihan kebijakan.
Penutup: Papua Sebelum Terlambat
Papua belum rusak.
Dan justru karena itu, ia seharusnya dilindungi, bukan dibuka.
Jika sawit—tanaman yang terbukti merusak ekosistem dan penyerapan air—tetap dipaksakan masuk ke hutan tropis terakhir Asia Tenggara, maka bencana di masa depan bukanlah kejutan. Ia adalah konsekuensi yang disengaja.
Sumatra sudah membayar mahal untuk kesalahan itu.
Pertanyaannya kini sederhana dan menentukan:
apakah Papua akan dijadikan pelajaran yang menyelamatkan, atau korban berikutnya dari pembangunan yang menolak belajar?