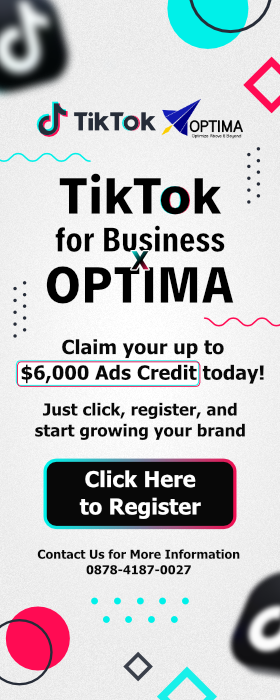CampusNet – Ketika bicara soal ideologi kekerasan ekstrem, banyak orang Indonesia masih membayangkannya sebagai sesuatu yang jauh: teroris bersenjata, jaringan bawah tanah, atau konflik di negara lain. Padahal hari ini, ancaman itu justru tumbuh pelan-pelan di ruang yang paling dekat dengan anak-anak kita: layar ponsel.
Ideologi kekerasan ekstrem di kalangan anak Indonesia bukan isu mayoritas, tetapi justru berbahaya karena bergerak senyap. Ia tidak datang dengan ledakan, melainkan dengan potongan video, potongan narasi, dan kalimat-kalimat provokatif yang dibungkus rapi atas nama kebenaran, identitas, atau bahkan moralitas.
Masalah utamanya bukan semata pada ideologinya, tetapi pada cara kekerasan dinormalisasi. Anak-anak diajarkan—secara implisit—bahwa marah itu wajar, membenci itu sah, dan melukai pihak lain bisa dibenarkan selama ada alasan ideologis di belakangnya. Pada titik ini, kekerasan tak lagi terasa ekstrem. Ia terasa logis.
Media sosial mempercepat proses itu. Algoritma tidak peduli pada nilai, hanya pada keterlibatan. Konten yang memicu emosi—amarah, takut, kebencian—akan selalu menang. Anak-anak yang sedang mencari jati diri dengan mudah terjebak dalam narasi hitam-putih: “kami vs mereka”, “benar vs sesat”, “pahlawan vs musuh”.
Ironisnya, respons kita sering kali justru keliru. Negara sibuk pada pendekatan keamanan, sementara rumah dan sekolah kerap abai. Anak yang menunjukkan sikap intoleran lebih sering dicap “nakal” atau “radikal” tanpa diajak bicara. Padahal radikalisasi tidak tumbuh dari kekosongan ide, melainkan dari kekosongan dialog.
Kita juga perlu jujur mengakui: pendidikan kita terlalu sering menekankan kepatuhan, bukan daya kritis. Anak diajarkan menghafal nilai, tetapi tidak dilatih mempertanyakan narasi. Akibatnya, ketika berhadapan dengan propaganda yang rapi dan emosional, mereka tidak punya alat untuk membedahnya.
Apakah ini berarti anak Indonesia sedang berada di ambang krisis ekstremisme? Tidak. Mayoritas tetap moderat, rasional, dan damai. Namun mengabaikan minoritas yang terpapar adalah kesalahan fatal. Sejarah menunjukkan, perubahan besar—termasuk yang destruktif—sering dimulai dari kelompok kecil yang militan.
Ideologi kekerasan ekstrem di kalangan anak Indonesia bukan soal agama, bukan soal ideologi semata. Ini soal ekosistem komunikasi yang gagal melindungi generasi muda dari narasi kebencian.
Jika kita terus menganggap ini isu pinggiran, maka suatu hari kita akan terkejut saat kekerasan tak lagi terasa asing—karena ia sudah tumbuh diam-diam di kepala anak-anak kita.
Dan saat itu terjadi, yang terlambat bukan penanganannya, tapi penyesalan kita.