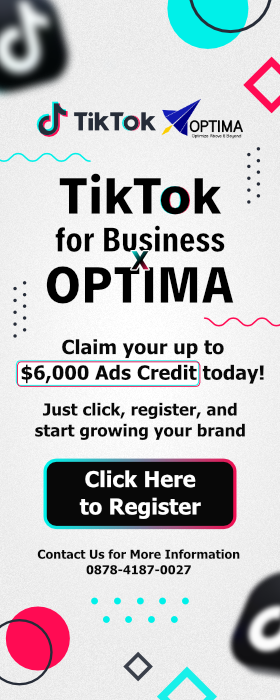CampusNet – Setiap kali rakyat bersuara, entah lewat aksi, petisi, atau unggahan media sosial, selalu muncul satu pertanyaan yang sama:
“Apakah suara kita benar-benar didengar?”
Dan entah kenapa, jawabannya hampir selalu — tidak.
Kita hidup di negara demokrasi, tapi demokrasi itu terasa seperti formalitas di atas kertas.
Rakyat boleh bicara, tapi keputusan tetap milik segelintir elit.
Kasus Soeharto: Ketika Sejarah Diputuskan Tanpa Dialog
Baru-baru ini, publik dikejutkan oleh kabar pengangkatan Soeharto sebagai Pahlawan Nasional.
Padahal, sebagian besar masyarakat — terutama korban pelanggaran HAM era Orde Baru — menolak keras keputusan ini.
Namun suara mereka tak diindahkan.
Pemerintah tetap melangkah, seolah-olah penolakan itu tak pernah ada.
Inilah ironi terbesar demokrasi: keputusan penting tentang sejarah bangsa justru dibuat tanpa mendengarkan sejarah yang hidup di ingatan rakyat.
Bagi banyak orang, ini bukan sekadar soal gelar, tapi tentang luka lama yang belum sembuh.
Tentang bagaimana negara lebih memilih mengafirmasi kekuasaan masa lalu, ketimbang menegakkan kebenaran masa kini.
Rempang: Ketika Warga Harus Tersingkir demi Proyek
Ada juga kasus yang terjadi di Pulau Rempang, Kepulauan Riau.
Ratusan warga harus tergusur demi proyek Rempang Eco City yang digadang-gadang sebagai proyek strategis nasional.
Padahal, warga sudah tinggal di sana turun-temurun selama ratusan tahun.
Mereka menolak — lewat aksi, mediasi, hingga jalur hukum.
Tapi lagi-lagi, suara rakyat kalah oleh kekuatan modal.
Negara tampak lebih cepat bergerak ketika investor bicara, bukan ketika rakyat menjerit.
Rempang menjadi simbol bahwa dalam praktiknya, negara lebih mendengar suara uang daripada suara manusia.
Masalahnya Bukan Rakyat yang Diam, Tapi Penguasa yang Tuli
Sering kali pemerintah menganggap rakyat “tidak peduli” atau “tidak mengerti.”
Padahal rakyat sudah bicara — hanya saja, tidak ada yang mau mendengar.
Demo dianggap mengganggu, kritik disebut kebencian, dan opini publik dikubur dengan istilah “hoaks” atau “tidak berdasar”.
Padahal, demokrasi bukan cuma tentang pemilu lima tahun sekali.
Demokrasi yang sehat berarti mendengar rakyat bahkan di luar musim kampanye.
Ketika Kekuasaan Lebih Nyaring dari Kebenaran
Selama ruang dialog ditutup dan kritik terus dibungkam,
maka suara rakyat akan selalu tenggelam oleh kebisingan kekuasaan.
Yang paling nyaring bukan lagi suara rakyat, tapi suara pejabat yang sibuk membela keputusan sendiri.
Kita menyaksikan bagaimana negara dengan mudah menafsirkan ulang sejarah, menggeser warga dari tanahnya, dan tetap menyebutnya “demi kemajuan.”
Padahal, kemajuan macam apa jika harus dibangun di atas penderitaan rakyatnya sendiri?
Akhirnya Kita Bertanya: Untuk Siapa Negara Ini?
Ketika negara lebih sibuk menjaga citra daripada mendengarkan rakyat,
demokrasi berubah jadi pertunjukan — lengkap dengan slogan, tapi tanpa empati.
Rakyat boleh bersuara, tapi hasilnya nihil.
Keputusan tetap dibuat di ruang rapat yang jauh dari suara publik.
Dan setiap kali rakyat mencoba bicara lebih keras,
negara menuduh mereka provokator.
Padahal, yang mereka minta cuma satu: didengar.
Penutup: Agar Kita Tak Lelah Berseru
Kita mungkin lelah bicara. Tapi diam bukan pilihan.
Sebab diam berarti menyetujui.
Dan jika rakyat berhenti bersuara, maka negeri ini akan sepenuhnya dikuasai oleh mereka yang tak pernah mau mendengar.
Jadi teruslah bicara.
Karena hari ini suara kita mungkin tak didengar, tapi esok — suara yang sama bisa jadi gema perubahan.
Baca juga: Soeharto Jadi Pahlawan Nasional: Ketika Kebenaran Kalah oleh Kekuasaan