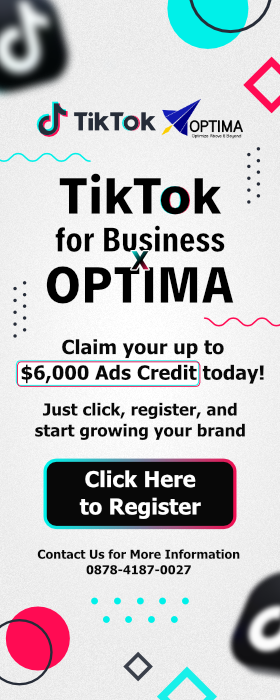CampusNet – Konflik internal PBNU yang menempatkan Yahya Cholil Staquf (Gus Yahya) dalam posisi terpojok bukan sekadar dinamika organisasi. Banyak pihak menilai bahwa ketegangan ini merupakan akumulasi dari gaya kepemimpinan yang terlalu sentralistis, kontroversial, dan tidak peka terhadap nilai serta kultur NU yang telah terbangun puluhan tahun.
Desakan agar Gus Yahya mundur bukan muncul secara tiba-tiba. Ia adalah hasil dari rangkaian keputusan yang memicu kekecewaan, kebingungan, bahkan kecurigaan. Dan penolakannya untuk mundur justru mempertegas persepsi bahwa kepemimpinan PBNU sedang dikuasai oleh ego personal serta agenda yang tidak sepenuhnya transparan.
Gaya Kepemimpinan yang Dinilai Mengabaikan Kultur NU
NU selama ini dikenal sebagai organisasi yang mengedepankan musyawarah, keluwesan sosial, dan kepekaan terhadap suasana kebatinan umat. Namun di masa kepemimpinan Gus Yahya, banyak keputusan justru terlihat “top-down” dan kurang mempertimbangkan basis struktural maupun kultural NU.
Beberapa langkahnya memicu pertanyaan besar:
- pemilihan narasumber asing yang menimbulkan kontroversi,
- sikap terbuka PBNU terhadap proyek tambang,
- pengelolaan program-program strategis yang cenderung elitis,
- serta minimnya ruang konsultasi yang melibatkan pengurus Syuriyah.
Dalam tradisi NU, sikap-sikap seperti ini dianggap menyimpang dari nilai-nilai dasar organisasi. Maka tidak heran bila risalah rapat Syuriyah yang meminta dirinya mundur dipandang sebagai reaksi wajar atas pola kepemimpinan yang tidak lagi sejalan dengan “naf” NU.
Penolakan Mundur: Rasional atau Ambisius?
Alasan Gus Yahya menolak mundur adalah karena ia dipilih Muktamar dan hanya Muktamar pula yang berhak mencopotnya. Benar dari sisi aturan, tetapi tidak otomatis benar dari sisi etika kepemimpinan.
Pemimpin yang kehilangan dukungan ulama dan struktural biasanya memilih langkah terhormat: mengundurkan diri demi menjaga marwah organisasi. Namun Gus Yahya bersikeras bertahan.
Inilah yang menimbulkan pertanyaan:
- Apakah ia mempertahankan jabatan demi NU atau demi otoritas pribadi?
- Apakah ia menjaga stabilitas organisasi atau menjaga pengaruh dalam proyek-proyek strategis?
- Apakah ia memegang prinsip, atau memegang akses terhadap kekuasaan?
Di titik ini, opini publik cenderung condong pada penilaian bahwa penolakannya bukan semata soal prosedur. Ada kepentingan yang lebih besar dan lebih dalam.
Isu Tambang: Bayang-Bayang Kepentingan yang Tidak Tepat di Ruang Ormas
Salah satu keputusan paling kontroversial PBNU adalah kesediaannya menerima konsesi tambang dari pemerintah. Secara formal, hal ini dibingkai sebagai upaya kemandirian ekonomi. Namun secara politik dan moral, keputusan itu sarat masalah.
Pertanyaan yang terus muncul adalah:
- Mengapa PBNU begitu antusias terhadap sektor tambang, yang penuh risiko korupsi, konflik agraria, dan kerusakan lingkungan?
- Mengapa mekanisme pengawasan dan struktur pengelolaannya tidak dibuka secara transparan?
- Siapa saja pihak internal yang terlibat?
- Apa jaminannya bahwa keputusan ini tidak menguntungkan kelompok tertentu?
Ketika dikaitkan dengan konflik internal, tidak sedikit pihak menilai bahwa “kekayaan” baru PBNU inilah yang menjadi sumber friksi terbesar. Jika tambang benar-benar dikelola, ia akan menjadi sumber daya strategis yang tidak kecil — dan potensi penyalahgunaannya sangat besar.
Dalam konteks ini, menolak mundur bisa dibaca sebagai upaya mempertahankan kontrol atas arah kebijakan tersebut.
Dampak Kepemimpinan yang Tidak Menyatu dengan Basis
NU selama ini kuat bukan karena pusatnya, tetapi karena jaringannya. Ketika ketua umum kehilangan koneksi dengan para kiai, PWNU, dan kader akar rumput, maka legitimasi sosial otomatis menyusut.
Dan inilah salah satu kritik paling tajam terhadap Gus Yahya:
ia terlalu sibuk mengonsolidasikan agenda besar di pusat, tetapi gagal menjaga kepercayaan di lingkaran yang paling menentukan — para sesepuh dan ulama kharismatik.
Konflik internal hari ini sebenarnya bukan antara “pro perubahan” dan “anti perubahan”. Ini adalah benturan antara:
- model kepemimpinan yang terlalu teknokratis dan sentralistis,
- melawan tradisi kebijaksanaan kolektif yang menjadi kekuatan NU sejak era para pendirinya.
Ketika pola kepemimpinan tidak lagi selaras dengan jantung organisasi, konflik adalah konsekuensi yang tak terhindarkan.
NU Butuh Pemimpin yang Menjaga Bukan Menguasai
Dari semua dinamika ini, satu kesimpulan mencuat:
NU membutuhkan pemimpin yang bisa menjadi penjaga nilai, bukan pengendali proyek.
Gus Yahya mungkin memiliki visi dan jejaring yang luas, tetapi ketika visi itu dijalankan tanpa kepekaan, tanpa kebersamaan, dan tanpa transparansi, maka ia berubah menjadi sumber kegaduhan.
Dan ketika kegaduhan itu sudah merusak kepercayaan internal, pemimpin yang baik seharusnya tahu kapan harus mengalah demi kemaslahatan yang lebih besar.
Baca juga: Konflik Gus Yahya & PBNU: Apa Penyebab Utamanya dan Kenapa Ia Menolak Mundur?