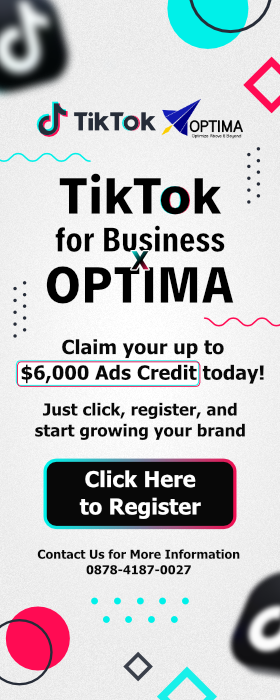CampusNet – Ketika banjir dan longsor melanda beberapa wilayah di Sumatra dalam beberapa waktu terakhir, pertanyaan publik muncul hampir bersamaan: mengapa belum juga ditetapkan sebagai bencana nasional? Air menenggelamkan rumah, jalan putus, korban jiwa berjatuhan, akses logistik terhambat, dan ribuan orang mengungsi. Namun bagi pemerintah, semua itu belum cukup “nasional”.
Di sinilah letak persoalannya: label bencana nasional tidak hanya soal rasa kemanusiaan, tapi juga soal politik, birokrasi, dan definisi yang kabur.
Status Bencana Nasional Bukan Sekadar Soal Besar Kecilnya Bencana
Secara teori, penetapan bencana nasional merujuk pada Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana. Ada sejumlah indikator yang dipertimbangkan: jumlah korban, luas wilayah terdampak, kerusakan infrastruktur, kerugian ekonomi, serta kemampuan daerah dalam menangani dampak bencana.
Masalahnya, hingga hari ini tidak ada aturan turunan yang menetapkan angka ambang yang tegas. Tidak ada kejelasan: berapa korban harus meninggal agar bisa disebut nasional? Berapa triliun kerugian? Berapa kabupaten terdampak? Semuanya bersifat interpretatif.
Akibatnya, status “bencana nasional” menjadi sesuatu yang sangat subjektif, tergantung pada sudut pandang pemerintah pusat, bukan pada rasa darurat yang dirasakan masyarakat.
Jika Daerah Masih ‘Dianggap Mampu’, Nasional Dianggap Tidak Perlu
Salah satu alasan klasik yang selalu muncul adalah: “Pemerintah daerah dinilai masih mampu menangani.”
Ini terdengar rasional di atas kertas — tapi bermasalah di lapangan. Dalam banyak kasus, kemampuan daerah “dipaksakan terlihat cukup” meski kenyataannya sumber daya mereka terbatas: alat berat minim, tenaga medis kurang, logistik terbatas, anggaran darurat tak mencukupi.
Selama kantor gubernur masih berdiri, rapat masih bisa digelar, dan bantuan masih bisa disalurkan meski lamban — maka pemerintah pusat merasa belum “darurat nasional”.
Pertanyaannya: apakah negara menunggu daerah benar-benar lumpuh dulu baru mau hadir penuh?
Ada Pertimbangan Politik dan Citra Negara
Status bencana nasional bukan hanya soal teknis penanganan, tapi juga soal citra. Penetapan ini dapat dianggap sebagai:
- Pengakuan bahwa negara gagal mengelola lingkungan dan tata ruang
- Bukti kerusakan ekologis yang sistemik
- Simbol lemahnya mitigasi dan perencanaan wilayah
Dengan kata lain, menetapkan bencana nasional berarti mengakui ada problem struktural — bukan sekadar hujan deras atau tanah labil, tapi juga pembabatan hutan, alih fungsi lahan, pertambangan, dan kebijakan tata ruang yang bermasalah.
Di sinilah tarik-menarik terjadi:
Lebih mudah menyebutnya “bencana daerah” daripada mengakui ini akibat kebijakan nasional yang gagal.
Label Nasional Berarti Tanggung Jawab Lebih Besar
Jika sudah berstatus nasional, maka:
- Kewenangan dan komando lebih banyak diambil alih pusat
- Anggaran yang dikucurkan jauh lebih besar
- Pengawasan publik dan internasional meningkat
- Standar rehabilitasi dan rekonstruksi lebih tinggi
Bagi pemerintah, ini bukan hanya tentang membantu, tapi juga soal beban politik, anggaran, dan ekspektasi.
Maka kadang, solusi yang dipilih adalah: membantu semaksimal mungkin, tapi tanpa “menaikkan level” statusnya.
Masalahnya, masyarakat tidak hidup dari status — mereka hidup dari kecepatan, ketepatan, dan kecukupan bantuan.
Kita Terjebak pada Istilah, Bukan Substansi
Yang ironis, saat perdebatan soal status terjadi di ruang-ruang diskusi, di Sumatra orang masih menyelamatkan anak-anak dari arus, mengangkut jenazah dari lumpur, dan bertahan hidup di pengungsian yang seadanya.
Di sini, frasa “bencana nasional” justru terlihat lebih politis daripada humanis. Ia kehilangan makna empatinya.
Sementara itu, alam tidak peduli label apa yang ditempel negara padanya.
Jadi, Apa yang Sebenarnya Kita Butuhkan?
Mungkin pertanyaan yang lebih penting bukan lagi:
“Layak atau tidak disebut bencana nasional?”
melainkan:
“Apakah negara benar-benar hadir, penuh, dan adil untuk semua warganya yang menjadi korban?”
Karena bagi korban, yang paling menyakitkan bukan hanya air atau longsor — tapi perasaan ditinggalkan dalam diam yang terlalu birokratis.
Baca juga: Bencana yang Berulang, Kesalahan yang Sama: Saatnya Mengakui Akar Masalah Krisis Iklim di Indonesia