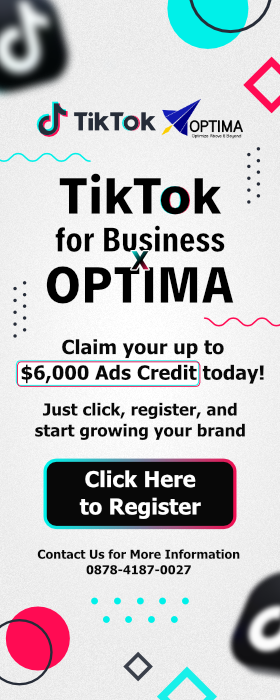CampusNet – Kasus skorsing seorang mahasiswa Universitas 17 Agustus 1945 (UTA’45) Jakarta karena rencana diskusi bertema “Soeharto Bukan Pahlawan” memantik perdebatan luas. Banyak yang menilai langkah kampus ini bukan sekadar tindakan disipliner biasa, tetapi mencerminkan kemunduran ruang akademik dan menghidupkan kembali ingatan publik pada praktik pembungkaman era Orde Baru. Pertanyaannya: apakah kampus hari ini benar-benar sedang mundur dari semangat demokrasi?
Diskusi yang Dihentikan, Mahasiswa yang Diskorsing
Rencana diskusi publik yang diinisiasi mahasiswa dianggap kampus sebagai kegiatan “politik praktis”. Melalui keputusan dekanat, mahasiswa tersebut diskors hingga akhir semester 2025/2026. Selama masa skorsing, ia dilarang mengikuti kuliah, organisasi mahasiswa, hingga kegiatan yang membawa nama kampus.
Bagi publik, tindakan ini terasa berlebihan. Tidak ada indikasi kekerasan, provokasi, atau pelanggaran tata tertib yang membahayakan. Yang ada hanyalah diskusi ilmiah mengenai figur sejarah yang memiliki rekam jejak panjang dan kompleks dalam perjalanan bangsa.
Di sinilah persoalan dimulai.
Apakah Ini Mengingatkan pada Pola Orde Baru?
Banyak pihak menganggap cara kampus menangani kasus ini serupa dengan pola-pola pembungkaman intelektual yang dulu terjadi pada era Orde Baru — masa ketika kritik terhadap Soeharto dianggap tabu, bahkan berbahaya.
1. Sensitivitas berlebihan terhadap kritik tokoh tertentu
Pada masa Orde Baru, menyebut nama Soeharto dalam konteks kritik bisa berujung intimidasi. Kini, ketika ruang akademik justru membatasi pembahasan sejarah secara kritis, wajar bila publik merasa ada kemunduran.
2. Kampus membatasi diskusi atas nama “stabilitas”
Narasi menjaga ketertiban sering kali menjadi alasan untuk meredam ruang diskusi. Namun sejarah membuktikan, pengekangan seperti ini justru menjadi pintu masuk menuju kultur anti-kritik.
3. Mekanisme sanksi yang top-down
Ketiadaan dialog, klarifikasi, dan proses sanksi berjenjang membuat keputusan ini terasa tidak transparan. Model pengambilan keputusan semacam ini sangat identik dengan kultur otoritarian masa lalu.
Kebebasan Akademik: Landasan Kampus yang Seharusnya Dijaga
Universitas adalah ruang untuk bertanya, mengkaji, mengkritik, dan menantang narasi umum — bukan sekadar tempat mengulang apa yang dianggap aman oleh institusi. Membahas Soeharto dan sejarah politik Indonesia adalah bagian dari pendidikan kritis, bukan politik praktis.
Jika kritik terhadap tokoh sejarah saja dibatasi, apa yang tersisa dari ruang akademik?
- Apakah mahasiswa hanya boleh membahas topik yang tidak sensitif?
- Apakah kampus hanya menerima pemikiran yang tidak menantang status quo?
- Apakah sejarah boleh dibahas hanya bila menguntungkan figur tertentu?
Jika ya, maka kita sedang mundur.
Efek Domino: Ketika Kampus Mulai Menutup Pintu
Skorsing seperti ini tidak hanya berdampak pada satu mahasiswa. Ada efek takut (chilling effect) yang bisa menyebar ke mahasiswa, dosen, bahkan organisasi kampus lainnya.
Beberapa potensi dampaknya:
- Mahasiswa enggan menggelar diskusi kritis.
- Dosen membatasi diri dalam mengangkat isu historis atau politik sensitif.
- Kampus lain bisa meniru pola serupa karena takut kontroversi.
Inilah yang berbahaya. Demokrasi tidak runtuh dalam semalam — ia melemah sedikit demi sedikit, dari pembungkaman kecil yang dianggap “biasa”.
Kenapa Kasus Ini Harus Dikritisi?
1. Ini menyangkut hak kebebasan akademik
Diskusi ilmiah seharusnya dilindungi, bukan dibungkam. Kritik terhadap figur sejarah adalah bagian dari pendidikan politik yang sehat.
2. Kampus sebagai penjaga demokrasi
Sejak Reformasi 1998, kampus menjadi arena penting untuk membangun budaya demokratis. Ketika kampus ikut membatasi ruang berpikir, demokrasi kehilangan salah satu penopang utamanya.
3. Menghindari normalisasi sensor
Hari ini tema Soeharto dilarang. Besok mungkin tema lain. Jika pembatasan ini tidak dikritisi, sensor perlahan menjadi normal.
Pelajaran Penting untuk Kampus dan Demokrasi
Kampus seharusnya merangkul perdebatan, bukan menghindarinya. Mengelola diskusi sensitif jauh lebih baik daripada menutupnya. Jika ada perbedaan pandangan, biarkan ruang akademik menjadi tempat adu argumen yang sehat — bukan tempat untuk menghukum.
Kebebasan akademik bukan ancaman bagi kampus. Justru sebaliknya: itulah yang menjaga kampus tetap relevan.
Kesimpulan: Kita Tidak Hidup di Orde Baru, tapi Bayangannya Masih Ada
Benar, Indonesia hari ini bukan Orde Baru. Negara tidak mengirim tentara ke kampus atau membredel media. Publik bisa bersuara, mahasiswa bisa melakukan perlawanan.
Namun ketika kampus membatasi pembahasan sejarah, menindak diskusi kritis, dan menggunakan sanksi sebagai alat kontrol, kita melihat bayangan Orde Baru masih berkeliaran.
Mengkritik masa lalu bukan tindakan politik praktis — itu adalah bagian dari tanggung jawab intelektual.
Dan kampus seharusnya menjadi ruang paling aman untuk melakukannya.
Baca juga: Pantaskah Soeharto Mendapatkan Gelar Pahlawan Nasional?