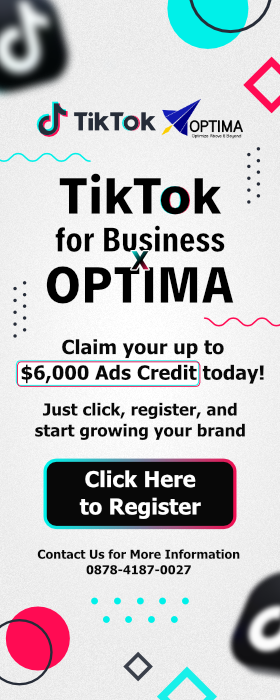CampusNet – Terbitnya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 48 Tahun 2025 tentang Penertiban Kawasan dan Tanah Terlantar kembali memantik perdebatan: benarkah tanah kosong bisa direbut negara?
Pertanyaan ini bukan sekadar soal hukum agraria. Ia menyentuh isu yang lebih besar — relasi antara hak milik warga dan perluasan kewenangan negara.
Secara prinsip, Indonesia memang tidak mengenal konsep kepemilikan tanah yang absolut. Sejak Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) 1960, setiap hak atas tanah mengandung fungsi sosial. Tanah tidak boleh hanya menjadi objek spekulasi atau dibiarkan tanpa manfaat.
PP 48/2025 hadir sebagai instrumen untuk menegaskan prinsip tersebut. Namun seperti banyak kebijakan agraria, persoalannya bukan pada niatnya — melainkan pada batas tafsir dan implementasinya.
Apa yang Diatur dalam PP Nomor 48 Tahun 2025?
PP 48/2025 memperbarui aturan sebelumnya dan memberi mekanisme lebih tegas dalam penertiban tanah terlantar. Tanah dapat ditetapkan sebagai terlantar apabila:
- Telah diberikan hak (SHM, HGB, HGU, Hak Pakai),
- Tidak dimanfaatkan atau tidak diusahakan sesuai peruntukan,
- Tidak menunjukkan itikad penggunaan,
- Tetap diabaikan setelah proses identifikasi dan peringatan administratif.
Setelah melalui tahapan tersebut, hak atas tanah dapat dihapus dan lahan kembali menjadi tanah negara.
Di atas kertas, tidak ada penyitaan mendadak. Ada prosedur. Ada peringatan. Ada evaluasi.
Namun regulasi ini juga memangkas dan menyederhanakan jalur administratif, sehingga proses penetapan bisa berlangsung lebih cepat dibanding aturan sebelumnya.
Fungsi Sosial atau Fleksibilitas Tafsir?
Prinsip fungsi sosial tanah penting dalam konteks ketimpangan agraria. Indonesia masih menghadapi masalah konsentrasi lahan dalam skala besar, sementara kebutuhan masyarakat terhadap akses tanah terus meningkat.
Penertiban lahan yang benar-benar mangkrak bisa menjadi bagian dari solusi.
Tetapi definisi “tidak dimanfaatkan” menjadi kunci.
Apakah tanah yang hanya dipagari dan dibersihkan termasuk dimanfaatkan?
Apakah tanah warisan yang belum dibangun karena keterbatasan modal masuk kategori terlantar?
Bagaimana jika pemilik menunggu perizinan atau kondisi ekonomi membaik?
Jika standar teknisnya tidak dijelaskan secara rinci dan transparan, maka frasa “tanah terlantar” bisa menjadi ruang tafsir yang elastis.
Dan dalam kebijakan agraria, tafsir yang elastis selalu memiliki dimensi politik.
Spekulasi Lahan vs Kekhawatiran Publik
Narasi resmi menyebut bahwa PP 48/2025 menyasar lahan skala besar yang tidak produktif — terutama konsesi usaha, perkebunan, pertambangan, atau perumahan yang mangkrak.
Jika itu yang benar-benar diprioritaskan, maka kebijakan ini dapat dibaca sebagai langkah korektif terhadap praktik spekulasi lahan.
Namun teks regulasi tidak secara eksplisit membedakan antara lahan korporasi ribuan hektare dan tanah kecil milik keluarga.
Secara hukum, semua hak atas tanah tetap bisa masuk kategori apabila dianggap memenuhi unsur “terlantar”.
Di sinilah muncul kekhawatiran:
apakah implementasinya akan konsisten menyasar spekulasi besar, atau justru lebih mudah menekan pemilik kecil yang lemah secara akses hukum?
Potensi Abuse of Power?
Setiap perluasan kewenangan negara selalu membawa dua kemungkinan: efektivitas atau penyalahgunaan.
Tanpa:
- Standar indikator pemanfaatan yang jelas,
- Transparansi daftar tanah yang sedang diproses,
- Mekanisme keberatan yang independen,
- Pengawasan publik yang kuat,
penertiban bisa bergeser dari instrumen reforma agraria menjadi ruang diskresi administratif yang luas. Dan diskresi yang luas, tanpa pengawasan, selalu berisiko.
Reforma Agraria atau Perluasan Kekuasaan?
PP Nomor 48 Tahun 2025 menegaskan bahwa tanah bukan sekadar aset pribadi, melainkan sumber daya sosial yang harus produktif. Secara normatif, itu sejalan dengan prinsip UUPA.
Namun keberhasilan aturan ini tidak ditentukan oleh teksnya, melainkan oleh keberpihakannya dalam implementasi. Tanah kosong memang bisa diambil alih negara — tetapi bukan secara otomatis dan bukan tanpa proses.
Pertanyaan besarnya bukan lagi apakah negara punya kewenangan.
Melainkan: kepada siapa kewenangan itu paling keras akan diterapkan?