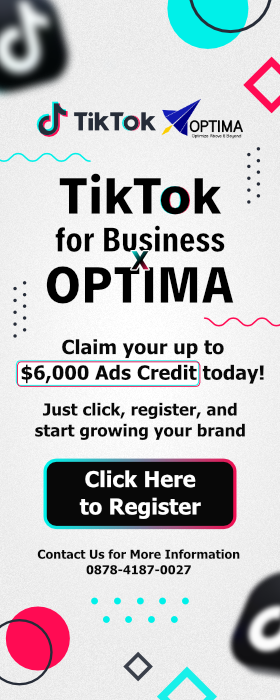CampusNet – Wacana mengembalikan Undang-Undang Dasar 1945 ke naskah awal kembali mencuat setelah Presiden Prabowo Subianto menyebut perlunya meninjau ulang konstitusi hasil amandemen reformasi. Sekilas, gagasan ini terdengar ideal: kembali ke “jati diri bangsa”, setia pada Pancasila, dan keluar dari sistem yang dianggap terlalu liberal. Namun, pertanyaannya bukan sekadar soal niat, melainkan apa konsekuensi nyata dari langkah tersebut bagi demokrasi Indonesia.
UUD 1945 naskah asli lahir dalam situasi darurat pasca-kemerdekaan. Para pendiri bangsa sendiri menyebut konstitusi itu bersifat sementara dan membuka ruang untuk disempurnakan. Karena itu, mengidealkan naskah awal tanpa membaca konteks sejarahnya justru berisiko menyesatkan. Sistem ketatanegaraan dalam UUD asli menempatkan Presiden sebagai figur yang sangat kuat, dengan MPR sebagai lembaga tertinggi negara. Rakyat tidak memilih Presiden secara langsung, dan mekanisme kontrol terhadap kekuasaan nyaris tidak memadai.
Reformasi 1998 mengubah itu semua bukan tanpa alasan. Amandemen UUD 1945 dilakukan sebagai respons atas pengalaman pahit kekuasaan yang terlalu terpusat, minim pengawasan, dan rentan disalahgunakan. Pemilihan Presiden langsung, pembatasan masa jabatan, penguatan hak asasi manusia, serta lahirnya Mahkamah Konstitusi adalah hasil dari kesadaran kolektif bahwa demokrasi membutuhkan rem, bukan hanya mesin.
Di sinilah letak persoalan utama wacana “kembali ke naskah awal”. Jika dilakukan secara utuh, langkah ini berpotensi menghapus capaian-capaian penting reformasi. Pemilihan Presiden bisa kembali ke tangan elite di MPR, sementara suara rakyat dipinggirkan. Hak asasi manusia yang kini dijamin secara konstitusional bisa kehilangan pijakan kuat. Dalam situasi politik yang semakin elitis, perubahan ini justru membuka ruang bagi konsolidasi kekuasaan, bukan partisipasi publik.
Pendukung wacana ini sering menegaskan bahwa yang dimaksud bukan kembali sepenuhnya, melainkan UUD 1945 asli dengan addendum terbatas. Namun, sampai hari ini, publik belum mendapatkan kejelasan: addendum versi siapa, untuk kepentingan siapa, dan siapa yang mengawasinya? Tanpa transparansi dan partisipasi publik yang luas, narasi “penyempurnaan konstitusi” mudah berubah menjadi proyek politik segelintir elite.
Konstitusi bukan sekadar dokumen hukum, melainkan kontrak sosial antara negara dan warga. Mengubahnya bukan perkara nostalgia, apalagi romantisme masa lalu. Jika demokrasi dianggap bermasalah hari ini, solusinya bukan menarik jam ke belakang, tetapi memperbaiki praktik politik, penegakan hukum, dan etika kekuasaan.
Mengembalikan UUD 1945 ke naskah awal, tanpa kehati-hatian dan kontrol publik yang ketat, berisiko menjadi langkah mundur yang dibungkus retorika kebangsaan. Indonesia tidak kekurangan simbol persatuan; yang dibutuhkan adalah keberanian untuk menjaga demokrasi tetap hidup, bahkan ketika ia terasa merepotkan bagi para penguasa.